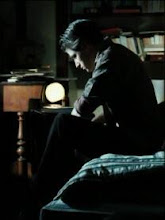HSBC Bank pernah melakukan survei pada pekerja formal di Indonesia terkait perencanaan setelah pensiun. Hasilnya, 30% responden sudah menyiapkan diri dalam bentuk investasi, sementara sisanya yang 70% mengandalkan bantuan keuangan anak-anaknya kelak.
Ada banyak orang tua mengandalkan anak-anaknya, dan anak-anak itu lalu harus menghidupi keluarganya sendiri juga menghidupi orang tuanya. Fenomena itulah yang lalu populer disebut “sandwich generation”—generasi yang terjepit dari atas dan bawah. Dari atas, orang tua menuntut bantuan. Dari bawah, ada kebutuhan si anak sendiri [apalagi kalau sudah punya keluarga sendiri.]
Sandwich generation sebenarnya tidak masalah, kalau si anak memang hidup berkelimpahan, atau setidaknya berkecukupan, sehingga bisa mengulurkan bantuan keuangan untuk orang tua yang sudah pensiun atau sudah sepuh dan tidak lagi bekerja. Tapi bagaimana jika si anak justru hidup pas-pasan?
Bagi banyak orang, hidup saja sudah susah. Menjalani kuliah sampai lulus, susah. Mencari kerja, susah. Memenuhi kebutuhan sehari-hari, susah. Menggapai cita-cita atau impian, susah. Jika generasi susah ini masih dituntut jadi “sandwich”, itu seperti menimpakan beban yang bertambah-tambah.
Sandwich generation, dalam perspektif saya, adalah hasil kekeliruan cara berpikir. Manusia senang “mengidealkan” masa depan—itulah inti masalahnya! Manusia senang membayangkan “hidup bahagia selama-lamanya”, lalu punya anak-anak yang mengurus mereka.
Yang jadi masalah, pola pikir semacam itu sebenarnya warisan masa lalu yang sudah tidak relevan. Seratus tahun lalu—apalagi seribu tahun lalu—jelas berbeda dengan zaman sekarang. Karena zaman sudah berubah, cara berpikir mestinya ikut berubah. Dan inilah masalahnya.
Kita didoktrin untuk percaya pada sesuatu yang sebenarnya hanya relevan di masa lalu. Akibatnya, banyak dari kita yang menjalani hidup di masa sekarang, tapi masih menggunakan pola pikir masa lalu. Sandwich generation hanyalah satu di antara banyak masalah lain yang kemudian lahir.
Di masa lalu belum ada globalisasi; anak masih hidup berdekatan dengan orang tua, meski sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Kenyataan itu lalu melahirkan pola pikir “orang tua mengandalkan anak”. Relevan di masa lalu, tapi bisa menjadi masalah di masa kini.
Globalisasi—yang dapat memisahkan anak dan orang tua hingga hidup sangat berjauhan—hanyalah satu hal. Masih ada hal-hal lain yang menjadikan doktrin masa lalu, khususnya terkait sandwich generation, sulit diterapkan di masa sekarang, dan bisa berbuah kekecewaan.
Seperti yang saya sebut tadi, masalah ini berawal dari kekacauan pola pikir. Orang tua di masa lalu berpikir anak adalah investasi yang menguntungkan, dan itu sah. Karena kehidupan di masa lalu memang memungkinkan untuk “menanamkan investasi pada anak-anak”.
Tapi berpikir “anak adalah investasi” di masa sekarang bisa menimbulkan aneka masalah, karena—kalau menggunakan perspektif investasi—“investasimu belum tentu menguntungkan, tapi malah bisa rugi besar”. Masalah bagi orang tua, juga masalah bagi si anak.
Anak zaman dulu mungkin mudah percaya pada aneka doktrin yang dicekokkan ke kepala mereka. Tapi anak zaman sekarang sudah mulai menyadari bahwa “anak tidak minta dilahirkan”. Kesadaran itu, entah kita sadar atau tidak, membawa implikasi yang luar biasa besar.
Anak tidak minta dilahirkan. Kalau kamu punya anak, itu keputusanmu, bukan keputusan si anak. Karena itu keputusanmu, kamulah yang bertanggung jawab, bukan sebaliknya. Semakin ke sini, semakin banyak anak yang sadar soal ini.
Kita meributkan sistem dan isme-isme, tapi yang kita ributkan selalu yang ada di luar sana; kapitalisme, sosialisme, liberalisme, dan aneka isme lain. Seiring dengan itu, kita melupakan sistem yang kita bangun sendiri, isme yang ada di kepala dan keyakinan kita sendiri.
Kita membangun sistem yang angkuh berdasar doktrin yang seharusnya mulai dibongkar dan dipertanyakan, kita membangun isme yang kita yakini benar padahal sudah harus dikaji ulang. Karena sistem dan isme yang disandarkan pada masa lalu hanya relevan untuk masa lalu.