Writing is essentially saying, “I have something I really want to tell you, but I don’t want to be anywhere near you, or give you any opportunity to talk back.”
Kalimat itu diucapkan oleh Ken Dee, seorang jurnalis internasional. Dan, kalau saya boleh menambahkan, “That’s an introvert’s dream.”
Baca: Media Online Paling Memuakkan
Belum lama, saya menerima telepon dari seseorang. Saya tidak mengenalnya, tapi dia mengenal saya. Berdasarkan penjelasannya, dia mendapatkan nomor ponsel saya dari seseorang yang sama-sama kami kenal. Dia memperkenalkan diri, dan menjelaskan maksudnya menelepon.
“Saya dari Penerbit X (sebuah penerbit di Indonesia), dan bermaksud mengajak Anda bekerja sama. Kami ingin menerbitkan karya Anda, dan...” Setelah menguraikan beberapa hal, dia menambahkan, “Untuk itu, kami juga akan meminta Anda untuk menghadiri peluncuran buku, wawancara, dan...” dan lain-lain syarat semacamnya, yang intinya mengharuskan saya menghadiri acara yang mereka bikin.
Sambil tersenyum, saya menjawab, “Sepertinya Anda salah orang. Saya bukan penulis yang seperti itu.”
Percakapan telepon itu selesai tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun. Dan, terus terang, itu bukan kejadian pertama. Sebelumnya, saya sudah beberapa kali menerima telepon dengan tawaran serupa—dari penerbit yang ingin menerbitkan karya saya, tapi mereka menetapkan syarat macam-macam, yang intinya saya harus “keluar”, “muncul”, atau apa pun istilahnya. Dan saya tidak pernah tertarik dengan tawaran semacam itu.
Ketika menetapkan diri menjadi penulis, saya berpikir bahwa profesi ini memungkinkan saya khusyuk bekerja tanpa harus keluar menemui orang-orang, tanpa harus mengikuti acara tetek bengek yang mengharuskan saya tampil, bahkan memungkinkan saya untuk tidak dikenal! Itu alasan dan latar belakang kenapa saya memilih jadi penulis!
Bagi yang mungkin belum tahu, sebelumnya saya justru aktif menjadi pembicara dibanding menulis. Selama masa-masa kuliah, hingga beberapa tahun setelah tidak lagi kuliah, saya lebih banyak berbicara di berbagai kampus dan di banyak tempat, dibanding menulis. Orang-orang senang mendengarkan saya berbicara, dan saya pun senang berbicara di hadapan mereka.
Selama waktu-waktu itu, saya tampil di banyak tempat, di berbagai forum, dan berbicara, berbicara, berbicara. Bahkan, kesenangan serta “kegilaan” saya saat berbicara pula, yang lalu ikut mempengaruhi gaya tulisan saya. (Untuk hal tersebut, dulu pernah saya ceritakan
di sini.)
Sampai kemudian, era media sosial lahir, dan menjadi bagian gaya hidup masyarakat kontemporer. Sejak ada Twitter, Facebook, Instagram, dan semacamnya, apa saja bisa masuk ke sana. Saya pun berpikir, “Jika aku masih aktif sebagai pembicara, foto-fotoku akan mudah didapat, dan orang-orang akan mudah mengenaliku.”
Sejak itu pula, saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan sejak itu semua undangan menjadi pembicara dari mana pun terpaksa saya tolak. Sampai saat ini. Bahkan ketika kampus almamater saya mengundang untuk berbicara di sana, saya tetap menolak. Mereka telah mencoba mengundang berkali-kali, dan saya telah menolak berkali-kali.
Intinya, saya tidak lagi bersedia muncul ke hadapan publik, untuk meminimalkan “tekanan psikologis” yang saya alami.
Saya
seorang introver, yang, sebenarnya, lebih nyaman saat sendirian. Fakta bahwa saya pernah aktif menjadi pembicara yang tampil di hadapan banyak orang, saya pikir itu “kecelakaan”. Kebetulan, saya dikaruniai kemampuan berbicara yang—bagi banyak orang—menarik, dan saya memanfaatkan karunia itu. Tetapi, sejujurnya, saya hanya nyaman ketika berbicara di depan forum, tapi tidak di luar forum.
Saya sering kebingungan saat harus berinteraksi dengan orang yang belum terlalu kenal, dan kami harus membicarakan hal-hal remeh-temeh seperti basa-basi dan semacamnya. Itu, bagi saya, jauh lebih sulit dibandingkan berbicara di forum yang dihadiri ratusan orang, yang mengharuskan saya membicarakan peradaban dunia dan nasib umat manusia. Dalam ilustrasi yang mudah, saya tidak tahu cara pedekate, meski tahu cara membuat wanita tergila-gila jika kami telah bersama.
Sebagai introver, saya menghadapi kenyataan “mengerikan” itu—sesuatu yang tampaknya tidak dipahami kebanyakan orang. Saya kurang bisa (dan sebenarnya malas) berbasa-basi, atau membicarakan hal-hal tolol yang tidak penting. Susahnya, dalam interaksi dengan orang lain (yang kita kenal maupun tidak), hal-hal semacam itu sulit dihindarkan.
Kalau kau orang terkenal—dalam arti orang-orang mengenalmu sebagai “Si Anu” karena fotomu terpampang di mana-mana, sehingga mudah dikenali—selalu ada kemungkinan orang akan mengenalimu saat kau berada di mana pun. Ketika itu terjadi, mau tak mau kau harus berinteraksi dengan mereka, entah sekadar basa-basi, atau membicarakan hal-hal remeh yang sangat tidak penting sekali. Karena, kalau tidak begitu, kau akan dikenal sebagai bangsat sombong. Jadi, agar kau tetap populer, dan orang tetap menyukaimu, kau harus murah senyum, ramah, bersedia basa-basi, meski sebenarnya kau tidak menginginkan.
Kenyataan seperti itulah yang tidak saya inginkan. Itu pula yang saya hindari.
Jadi, seperti yang disebut tadi, saya mengundurkan diri dari aktivitas sebagai pembicara, tepat ketika era media sosial mulai menjadi bagian gaya hidup masyarakat kita. Karena saya tidak ingin orang-orang mudah mengenali saya. Karena saya tidak ingin mengalami tekanan psikologis yang hanya dapat saya pahami sendiri.
Sejak itu pula, saya memutuskan untuk sepenuhnya menjadi penulis, karena saya pikir profesi sebagai penulis tidak mengharuskan saya tampil di mana pun, sekaligus memungkinkan saya untuk tidak dikenali. Sebagai penulis, saya hanya perlu menulis, membuat naskah, dan membiarkan penerbit menangani urusan selanjutnya.
Kenyataannya, saya nyaman menjalani profesi menulis, karena memungkinkan saya menjalani gaya hidup yang saya inginkan. Saya bisa keluyuran ke mana pun tanpa dikenal orang, meski mungkin mereka mengenal nama saya, atau meski mereka membaca buku dan tulisan-tulisan saya. Sebagai penulis, saya menawarkan karya, bukan menawarkan diri saya. Mereka boleh mengenal nama saya, menikmati karya saya, tapi cukuplah sebatas itu. Saya ingin tetap menjalani kehidupan dengan cara saya sendiri.
Karena latar belakang itu pula, terus terang, saya sangat selektif dalam memilih penerbit atau media untuk menerbitkan tulisan saya. Sebisa mungkin, saya hanya menjalin hubungan dengan penerbit dan media yang membebaskan penulis untuk tampil atau tidak, untuk menghadiri acara tetek bengek atau tidak. Pendeknya, saya hanya memilih penerbit dan media yang membebaskan saya untuk tidak dikenal!
Tentu saya senang dan menghargai jika penerbit mempromosikan buku saya. Tetapi, meski begitu, saya tetap tidak akan bersedia jika diminta muncul—semisal menghadiri peluncuran buku, wawancara, dan semacamnya—meski dengan alasan untuk promosi. Dan saya bersyukur, karena di Indonesia ada penerbit-penerbit yang bisa memahami penulisnya, sehingga saya tetap dapat menerbitkan buku sampai sekarang.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah penulis seperti saya hanya saya seorang, ataukah ada penulis-penulis lain yang juga seperti saya?
Mari saya ceritakan beberapa penulis yang saya kenal, yang juga memiliki “kelainan” seperti saya.
Beberapa tahun lalu, saya mengobrol dengan seorang teman yang juga penulis. Waktu itu dia baru menyelesaikan naskah novel, dan kami membicarakan kemungkinan penerbit mana yang paling tepat untuk naskahnya. Ketika saya menyebut satu nama penerbit, dia menjawab, “Aku suka penerbit itu, tapi sepertinya mereka mengharuskan penulis untuk aktif (maksudnya aktif dalam promosi, termasuk menghadiri launching buku, dan semacamnya.)”
Belakangan, naskah novel itu dikirim ke Gramedia Pustaka Utama, dan telah lama terbit. Jika saya sebutkan judulnya, atau nama penulisnya, kemungkinan besar kalian kenal.
Terkait Gramedia Pustaka Utama (GPU), ada banyak teman saya yang sangat “fanatik”—dalam arti mereka hanya mau naskah mereka diterbitkan GPU. Alasannya bukan karena GPU terkenal sebagai penerbit besar. Alasan kenapa banyak penulis—khususnya yang saya kenal—sangat “fanatik” pada GPU, karena GPU (dan penerbit lain di bawah Kompas-Gramedia Group) sangat memahami penulisnya!
Kalau kau ingin menerbitkan buku di GPU, yang kaubutuhkan hanya naskah bagus! Asal naskahmu bagus, berkualitas, dan layak jual—GPU akan menerima dan menerbitkan, dan tidak ada tetek bengek lain yang memberatkan. Setidaknya, itulah yang saya dan teman-teman alami, saat kami bekerja sama dengan mereka. Kami hanya perlu menulis naskah bagus, memenuhi standar mereka, dan selesai. Di luar urusan itu, semua bersifat opsional.
Sebagai contoh mudah, GPU tidak mewajibkanmu melampirkan foto untuk buku atau untuk tujuan apa pun. Kalau penulis ingin melampirkan fotonya, agar tampil di buku, silakan. Tapi kalau pun tidak, juga tidak masalah.
Jangankan foto, GPU bahkan tidak meminta fotokopi KTP penulis! Jika naskahmu diterbitkan GPU, yang perlu kaulakukan hanya menuliskan nama dan alamat lengkap (untuk urusan surat menyurat dan pengiriman bukti terbit), nomor rekening (untuk pengiriman royalti), dan nomor NPWP (untuk urusan pajak). Sudah, tidak ada tetek bengek lain!
Di luar itu—setidaknya yang pernah saya dan teman-teman alami—GPU juga tidak mengharuskanmu melakukan hal-hal yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Misalnya, kalau kau mau mempromosikan bukumu, itu bagus. Tapi kalau pun tidak, juga tidak apa-apa, dan GPU akan tetap menerbitkan bukumu selanjutnya, kalau naskahmu memang memenuhi standar mereka.
Kenyataan-kenyataan itulah yang membuat banyak penulis—khususnya yang saya kenal—sangat “fanatik” pada GPU, karena mereka menilai GPU sebagai penerbit yang benar-benar memahami mereka. Faktanya, banyak penulis GPU yang sangat terkenal, tapi sosoknya tak pernah kita lihat. Jangankan sosoknya, bahkan fotonya pun belum pernah kita lihat! Oh, well, itulah hebatnya dunia kepenulisan, dan karena itulah saya memilih menjadi penulis!
Sekali lagi, saya memilih menjadi penulis, karena tidak ingin dikenal. Kalau saya ingin dikenal, saya tidak akan jadi penulis... tapi jadi artis!
Jadi, ketika ada penerbit mengajak saya bekerja sama, tapi mengharuskan saya tampil dan menjalani tetek bengek semacamnya, terus terang saya tidak tertarik. Saya bukan pemula yang butuh popularitas. Saya profesional yang hanya ingin bekerja. Kalau orang-orang mengenal nama saya, dan menyukai karya yang saya hasilkan, silakan. Tapi saya ingin tetap menjalani kehidupan sebagaimana yang saya inginkan, tanpa harus terusik atau terganggu gara-gara “terkenal”.
Penerbit (dan media) yang baik bukan sekadar penerbit yang jujur dan profesional, tapi yang juga dapat memahami bahwa setiap individu (dalam hal ini penulis) bisa berbeda, sehingga lebih mampu berempati. Memang, sebagian orang menjadi penulis dengan harapan agar sosoknya dikenal. Tetapi ada sebagian lain yang menjadi penulis justru karena ingin sosoknya tidak dikenal. Saya termasuk golongan kedua.
Manakah yang lebih baik? Oh, ini hanya soal pilihan. Setiap orang tentu punya hak untuk dikenal, sebagaimana setiap orang juga punya hak untuk tidak dikenal. Kita tidak bisa memaksa Dee Lestari agar tidak muncul ke hadapan publik, sebagaimana kita tidak bisa memaksa Ilana Tan agar memunculkan diri. Itu hak dan pilihan masing-masing penulis—untuk dikenal, atau untuk tidak dikenal.
Di catatan mendatang, saya akan meneruskan catatan ini dengan menjelaskan bagaimana cara menjadi kaya—dan menghasilkan puluhan juta per bulan dari menulis—bahkan umpama kau tidak terkenal.

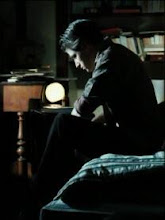

- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact