Saiki jamane jaman edan
yen ora edan ora keduman
sak bejo-bejone wong kang edan
isih bejo wong kang eling lan waspada
Sekarang adalah zaman kegilaan
kalau tidak gila tidak mendapat bagian
(tetapi) seberuntung apa pun mereka yang gila
masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada
—Ronggowarsito
Dari dulu saya kagum pada orang gila, sebentuk kekaguman yang lahir dari semacam perasaan, “Aku ingin seperti mereka, tapi tidak bisa.”
Ya, dari dulu saya ingin seperti orang gila, menjalani kehidupan seperti mereka, tapi terbentur kenyataan mengerikan, yaitu saya waras. Atau, setidaknya, orang-orang menganggap saya waras. Akibatnya, saya malu—dan tidak enak pada lingkungan—jika menjalani kehidupan seperti orang gila. Dalam hal ini, saya kalah dengan orang gila, karena mereka tidak terbebani perasaan apa pun dalam menjalani kehidupan.
Kelebihan yang dimiliki orang-orang gila, yang tidak dimiliki orang-orang waras adalah... kebebasan.
Kebebasan adalah privilese yang hanya dimiliki segelintir orang di tengah masyarakat, dan hanya orang-orang gila yang memiliki. Kalau kau tidak gila, jangan mimpi punya kebebasan. Karena masyarakat di sekelilingmu telah menyiapkan belenggu untuk mengerangkeng kewarasanmu.
Kehidupan orang-orang waras—setidaknya dalam pandangan saya—adalah kehidupan menyedihkan, karena penuh tekanan. Bahkan sejak lahir pun, orang-orang waras telah ditekan oleh sistem masyarakat. Setiap kali bayi lahir, masyarakat akan memastikan bayi itu waras seperti mereka, dalam arti tumbuh besar dan dewasa seperti mereka, menjalani kehidupan seperti mereka, pendeknya harus memiliki pilihan hidup yang seragam dengan mereka.
Masyarakat adalah tirani. Dan kita semua—orang-orang waras—menjadi korban serta budaknya.
Ketika seorang bayi telah tumbuh dan memasuki usia 3 atau 4 tahun, masyarakat mulai menggunakan kekuasaan tirani mereka untuk membelenggu. Belenggu itu bisa dalam bentuk pertanyaan kepada orang tua si bayi, “Anakmu sudah 4 tahun, kok belum masuk playgroup?”
Anak berusia 4 tahun belum bisa menentukan pilihan sendiri—mau masuk playgroup atau tidak. Karenanya, nasib si anak akan ditentukan orang tuanya. Karena orang tuanya waras, maka si orang tua pun memasukkannya ke playgroup atau PAUD, atau apa pun sebutannya. Yang penting masyarakat tidak bertanya-tanya lagi. Terlepas apakah si anak menikmati suasana di sana atau tidak, persetan. Yang penting orang tua tidak tertekan karena ditanya-tanya masyarakat.
Setelah “lulus” dari playgroup atau PAUD, nasib si anak sudah bisa diramalkan. Ia akan dimasukkan ke TK. Jika tidak, masyarakat akan ribut, “Anakmu kok belum masuk TK?”
Maka si anak pun kemudian masuk TK. Terlepas dia senang atau tidak menjalaninya, persetan. Yang penting orang tuanya tenteram, karena tidak lagi ditekan dan ditanya-tanya masyarakat.
Lalu apa yang terjadi ketika si anak lulus TK? Kita semua tahu jawabannya. Dia akan masuk SD, SMP, SMA, atau apa pun sebutannya. Selama menjalani jenjang demi jenjang pendidikan itu, setiap anak akan menghadapi tekanan demi tekanan—dari teman sebaya, dari guru-guru di sekolah, dari pergaulan, dari lingkungan, dari masyarakat, hingga tekanan dari orang tua sendiri.
Tapi nasib buruk mereka masih panjang.
Setelah lulus SMA, ada yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, ada pula yang tidak. Tetapi, terlepas apakah seseorang melanjutkan ke Perguruan Tinggi atau tidak, yang jelas mereka akan terus menghadapi tekanan masyarakat. Jika mereka tampak menganggur, masyarakat akan nyinyir, dan bertanya-tanya, “Sudah lulus kok menganggur?”
Maka mereka pun membabi-buta mencari kerja. Setelah bertahun-tahun ditekan oleh sesuatu yang disebut “sekolah”, mereka kini harus menghadapi tekanan baru—persaingan mencari kerja. Makin hari, kita tahu, mencari dan menemukan pekerjaan kian sulit. Tapi masyarakat tidak peduli. Bagi mereka, yang penting kau kerja, sialan! Biar tampak seperti orang waras!
Mencari kerja adalah satu hal, dan menemukan pekerjaan adalah hal lain. Bisa jadi, setelah menemukan pekerjaan, mereka tidak langsung cocok. Entah dengan pekerjaan yang dihadapi, atau dengan lingkungan kerja dan suasana yang dialami. Tetapi, daripada harus menghadapi tekanan masyarakat, banyak dari mereka yang terpaksa menelan kepahitan di tempat kerja, demi bisa “dianggap waras”.
Dan “pekerjaan waras” versi masyarakat adalah... kau harus tampak berangkat kerja pagi hari, lalu pulang sore hari. Kalau bisa, berseragam dan bersepatu. Kalau tidak begitu, kadar kewarasanmu kurang optimal. Terlepas berapa pun gaji atau penghasilanmu, persetan. Yang penting kau berangkat pagi dan pulang sore, dan memakai sepatu!
Setelah tampak waras karena memiliki pekerjaan—apalagi juga bersepatu—apakah tekanan yang dihadapi orang-orang sudah berhenti? Oh, belum! Masyarakat sangat tahu bagaimana menyiksamu habis-habisan, dan kali ini mereka akan nyinyir, “Sudah kerja, kapan kawin?”
Mula-mula, mungkin, orang cuma tersenyum menghadapi tekanan berupa pertanyaan bangsat itu. Tetapi, kita tahu, batas pertahanan setiap orang tidak sekuat Tembok Cina. Ada banyak dari kita yang termakan hasutan dan tekanan pertanyaan “kapan kawin?”, lalu buru-buru mencari pasangan.
Mereka yang buru-buru mencari pasangan bisa karena memang sudah ngebet kawin, bisa karena termakan rayuan dan hasutan masyarakat yang mengatakan “menikah akan bahagia dan segala macam”, atau bisa pula karena tidak tahan menghadapi tekanan berupa pertanyaan “kapan kawin?” terus menerus. Jadi, mereka pun berusaha mencari dan menemukan pasangan secepatnya, agar masyarakat berhenti nyinyir.
Dan setelah mereka menikah, apakah masyarakat lalu diam? Oh, hell, tentu saja tidak! Masyarakat adalah tirani yang kejam, dan keparat-keparat itu sangat tahu bagaimana melakukan penyiksaan yang sangat mengerikan—untuk pikiranmu, untuk jiwamu, untuk hidupmu. Sebelum kau berdarah-darah dalam luka, sebelum kau sekarat dalam derita, masyarakat akan terus bersuara.
Setelah orang menikah, masyarakat akan kembali bertanya, “Kapan punya anak?” Kalau kau telah menikah hingga dua tahun, dan kau beserta pasanganmu belum punya anak, setumpuk tuduhan akan dilemparkan kepadamu. Dari tuduhan mandul, impoten, frigid, terkutuk, sampai tuduhan-tuduhan biadab lain yang tak pernah kaubayangkan. Maka, tidak ada jalan lain, kau harus punya anak, secepatnya!
Lalu anak-anak tak berdosa dilahirkan, demi tuntutan masyarakat, demi membungkam kebejatan cocot mereka. Sebagian anak yang dilahirkan itu beruntung, karena memiliki orang tua pengasih, dan bisa memberi kehidupan yang layak. Tapi sebagian lain harus menerima takdir mengerikan karena orang tuanya begitu kejam, dan tak mampu memberi penghidupan yang layak.
Setelah orang punya satu anak, masyarakat akan kembali berbisa. Kali ini, bisa racun yang mereka semburkan adalah, “Kapan nambah anak?”
Kalau kau sudah menikah, dan punya satu anak, masyarakat belum rela. Kau harus punya banyak anak, atau setidaknya lebih dari satu, agar mereka menganggapmu waras. Dan keparat-keparat yang disebut masyarakat itu sangat tahu cara menipumu. Mereka bisa mengatakan, “banyak anak banyak rezeki,” atau “setiap anak memiliki rezeki sendiri,”, sampai desisan klise berbunyi, “tak perlu khawatir.”
Mungkin mereka memang buta. Meski di mana-mana ada jutaan anak telantar, mereka tidak malu mengatakan, “Banyak anak banyak rezeki”. Meski di sekeliling ada banyak anak kelaparan dan penuh derita, mereka tidak risih mengatakan, “Setiap anak memiliki rezeki sendiri”. Dan meski di banyak tempat ada anak-anak teraniaya akibat tekanan stres yang dihadapi orang tuanya, masyarakat tidak malu mengatakan, “Tak perlu khawatir.”
Seperti menghadapi tekanan pertanyaan “kapan kawin?”, ada banyak orang yang tak mampu menghadapi tekanan pertanyaan “kapan punya anak?” dan “kapan nambah anak?” Maka anak-anak tak berdosa dilahirkan dan terus dilahirkan. Mereka dilahirkan bukan dengan tujuan apa pun, melainkan demi membungkam cocot orang-orang, demi dianggap sama oleh masyarakat.
Dan, untuk itu, ada jutaan pasangan yang harus montang-manting menghadapi kehidupan berat, ada banyak lelaki yang harus menghadapi kenyataan hidup yang kejam, ada banyak wanita yang menangis diam-diam menghadapi beratnya hidup, dan ada banyak anak tak berdosa yang telantar, kelaparan, terluka, terluka, terluka....
Lalu anak-anak yang dilahirkan itu tumbuh seperti orang tua mereka. Saat baru saja bisa bernapas tenang, mereka sudah harus masuk playgroup. Lalu TK, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA, dan seterusnya. Setelah itu, tekanan demi tekanan akan terus menimpa mereka, persis seperti yang dihadapi orang tua mereka dulu. Dan mereka akan kembali melahirkan anak-anak malang, persis seperti saat mereka dilahirkan.
Sampai di sini, sudahkah kita melihat sesuatu yang mengerikan?
Orang-orang menjalani kehidupan tidak dengan kesadaran, melainkan dengan tekanan demi tekanan. Mereka bersekolah bukan karena kesadaran, tetapi demi dianggap sama seperti orang lain. Mereka bekerja bukan dengan kesadaran, melainkan karena menghadapi tekanan lingkungan.
Mereka menikah bukan dengan kesadaran, tapi demi membungkam orang-orang di sekitar, atau karena tertipu oleh bualan masyarakat. Mereka pun punya anak bukan karena kesadaran, melainkan karena tekanan masyarakatnya. Dan kehidupan menyedihkan semacam itu—hidup tanpa kesadaran—diwariskan turun temurun, dari orang tua kepada anaknya, dan terus berlanjut, dari generasi ke generasi.
Demi Tuhan dan demi para malaikat yang suci, kehidupan macam apa sebenarnya yang kita jalani?
Karena itulah, saya iri campur kagum pada orang-orang gila. Mereka bisa menjalani kehidupan dengan tenang, tenteram, tanpa khawatir dianggap berbeda dengan masyarakatnya. Hanya orang gila yang memiliki kebebasan, dalam hal ini kebebasan untuk menjalani hidup. Tanpa tekanan, tanpa pertanyaan, tanpa nyinyiran. Bahkan kalau pun orang-orang gila dinyinyiri, mereka hanya tertawa.
Saya ingin menjadi orang gila, karena tampaknya menjadi gila adalah satu-satunya jalan melepaskan diri dari tekanan masyarakat. Sistem nilai seperti apa pun tak berlaku bagi orang gila, dan mereka benar-benar bebas, merdeka. Orang-orang gila menjalani kehidupan sesuai pilihan sendiri, tanpa tekanan dan belenggu tirani.
Hanya orang gila yang bisa ngoceh panjang lebar tanpa khawatir dianggap gila. Hanya orang gila yang bisa menjalani kehidupan sesuai pilihan tanpa khawatir menjadi bahan gunjingan. Hanya orang gila yang bisa berpenampilan seperti apa pun tanpa khawatir dianggap ketinggalan zaman. Hanya orang gila yang bisa tenang dan damai dalam kehidupan, tanpa harus menghadapi pertanyaan terkutuk berbunyi “kapan?”
Alangkah indah menjalani kehidupan orang gila, dan alangkah susah menjalani kehidupan orang waras. Orang gila punya hak untuk hidup bebas dan merdeka, orang-orang waras tidak punya. Orang gila menjalani kehidupan dengan berdiri di atas kaki sendiri, orang-orang waras menjalani kehidupan dengan belenggu dan rantai tirani.
Dan... memikirkan semua itu, saya bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang waras, dan siapakah sebenarnya yang gila?
Demokrasi itu absurd, kalau dipikir-pikir. Kekuasaan ada di tangan rakyat, katanya. Tapi kenyataan rakyat justru tak punya kuasa apa-apa.
Demokrasi mirip perkawinan; sama-sama tampak indah, tapi sebenarnya jebakan. Terdengar bagus saat dipromosikan, tapi pahit dalam kenyataan.
Teori demokrasi: Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Teori perkawinan: Dari cinta, oleh cinta, untuk cinta kita.
Kenyataan: NGAPUSI.
Janji demokrasi: Rakyat senang, wakil rakyat senang.
Janji perkawinan: Tenteram, bahagia, lancar rezeki.
Realitas: NGAPUSI.
Masalah demokrasi: Orang-orang hanya menyuguhkan
hal-hal teoritis, tapi melupakan fakta yang mungkin terjadi.
Masalah perkawinan: SAMA.
Secara teoritis, demokrasi adalah sistem yang baik.
Sayang, realitas tak selalu sesuai dengan teori.
Perkawinan? PODO WAE.
Dalam pikiranku, perkawinan adalah... kau memasang borgol di satu tanganmu, dan meminta orang lain memasukkan tangannya di borgol yang sama.
Orang yang suka mempromosikan indahnya perkawinan, tak jauh beda dengan politisi ngomong keadilan demokrasi. Sama-sama tahu itu bohong.
Kenapa banyak orang BERUSAHA MEYAKINKAN bahwa perkawinan itu indah, membahagiakan, dan taik kucing lainnya? Karena REALITASNYA tidak begitu.
Kalau memang perkawinan begitu indah, membuat tenteram dan bahagia, LALU KENAPA KAU HARUS MATI-MATIAN MEYAKINKAN ORANG LAIN?
Kalau kau berusaha meyakinkan sesuatu agar aku percaya, padahal aku bisa tahu tanpa diyakinkan, jawabannya mutlak: KENYATAANNYA TIDAK BEGITU.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 8 Juli 2017.
Demokrasi mirip perkawinan; sama-sama tampak indah, tapi sebenarnya jebakan. Terdengar bagus saat dipromosikan, tapi pahit dalam kenyataan.
Teori demokrasi: Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Teori perkawinan: Dari cinta, oleh cinta, untuk cinta kita.
Kenyataan: NGAPUSI.
Janji demokrasi: Rakyat senang, wakil rakyat senang.
Janji perkawinan: Tenteram, bahagia, lancar rezeki.
Realitas: NGAPUSI.
Masalah demokrasi: Orang-orang hanya menyuguhkan
hal-hal teoritis, tapi melupakan fakta yang mungkin terjadi.
Masalah perkawinan: SAMA.
Secara teoritis, demokrasi adalah sistem yang baik.
Sayang, realitas tak selalu sesuai dengan teori.
Perkawinan? PODO WAE.
Dalam pikiranku, perkawinan adalah... kau memasang borgol di satu tanganmu, dan meminta orang lain memasukkan tangannya di borgol yang sama.
Orang yang suka mempromosikan indahnya perkawinan, tak jauh beda dengan politisi ngomong keadilan demokrasi. Sama-sama tahu itu bohong.
Kenapa banyak orang BERUSAHA MEYAKINKAN bahwa perkawinan itu indah, membahagiakan, dan taik kucing lainnya? Karena REALITASNYA tidak begitu.
Kalau memang perkawinan begitu indah, membuat tenteram dan bahagia, LALU KENAPA KAU HARUS MATI-MATIAN MEYAKINKAN ORANG LAIN?
Kalau kau berusaha meyakinkan sesuatu agar aku percaya, padahal aku bisa tahu tanpa diyakinkan, jawabannya mutlak: KENYATAANNYA TIDAK BEGITU.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 8 Juli 2017.
Keliru berawal dari pikiran. Karena berpikir keliru,
kita bertindak keliru, dan tidak menyadari itu keliru.
Kenyataan tergantung pikiranmu.
Dulu, sebelum saya lahir, di Pekalongan ada sebuah bioskop yang berdiri di belakang jembatan, di sisi sebelah sungai. Lokasinya di Jalan Hayam Wuruk. Hampir semua orang Pekalongan—khususnya yang telah cukup puber pada 1990-an—tahu bioskop tersebut. Itu salah satu bioskop tertua di Pekalongan.
Jadi, di Jalan Hayam Wuruk ada jembatan, dan di bawahnya mengalir sungai yang memotong jalan. Di belakang jembatan, bersisian dengan sungai, ada tanah lapang yang tersambung dengan sebuah perkampungan. Di tanah lapang itulah berdiri sebuah bioskop—jauh sebelum saya lahir. Bioskop itu aktif pada era 1970-an.
Saya tidak yakin apa nama bioskop tersebut. Dulu, saya pernah mencoba menanyakan pada beberapa orang tua yang saya kenal, mengenai nama bioskop di sana. Tapi jawaban yang saya terima simpang siur. Sebagian orang menjelaskan, bioskop di sana bernama “Remaja”. Tetapi, sebagian lain mengatakan Bioskop Remaja bukan terletak di Jalan Hayam Wuruk, melainkan di tempat lain.
Sekadar catatan, di Pekalongan ada restoran bernama “Remaja”, lokasinya cukup dekat dari Jalan Hayam Wuruk. Restoran itu sekarang sudah tidak ada, tapi saya sempat menyaksikan keberadaannya ketika masih kecil dulu. Berdasarkan penuturan beberapa orang tua, Restoran Remaja dulunya adalah bioskop bernama “Remaja”. Jadi, menurut mereka, Bioskop Remaja berada di tempat yang kemudian berubah menjadi Restoran Remaja—bukan di Jalan Hayam Wuruk.
Karena informasi mengenai nama bioskop di Jalan Hayam Wuruk masih simpang siur, kita sebut saja Bioskop X. Ketika saya lahir, Bioskop X sudah tidak beroperasi, tapi gedung atau bangunannya masih ada, bahkan masih utuh. Karenanya, di masa kecil dulu, saya masih melihat keberadaan gedung tersebut. Orang-orang memberitahu, bahwa gedung itu dulunya bioskop.
Dalam ingatan saya, gedung itu tampak kuno tapi kukuh, dengan warna cat yang telah pudar, hingga menampakkan dinding-dinding kusam. Bahkan, menurut yang saya dengar waktu itu, di dalam gedung masih terdapat kursi-kursi yang digunakan penonton bioskop untuk menonton film. Jadi, bisa dibilang, isi bioskop itu masih lengkap, tapi tidak lagi beroperasi.
Sampai suatu hari, gedung itu terbakar. Waktu itu saya kelas tiga SD. Seperti anak-anak lain yang mudah penasaran dengan apa pun, saya bersama teman-teman berlari-lari ke sana, ingin menyaksikan kebakaran yang terjadi. Gedung bekas bioskop itu memang terbakar. Dari seberang jalan, kami menyaksikan api menjilat-jilat, asap membubung ke langit, sementara petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan.
Kini, saat saya menulis catatan ini, gedung bioskop di Jalan Hayam Wuruk sudah tidak ada, bahkan bekasnya pun sudah tak tampak. Tetapi, saya masih ingat betul keberadaan gedung bioskop tersebut, saat masih kukuh berdiri, hingga saya menyaksikannya terbakar suatu hari.
Bertahun-tahun kemudian sejak peristiwa itu, tepatnya pada 2016, ada seseorang dari luar kota yang memperlihatkan foto-foto kepada saya—foto-foto suasana Pekalongan masa lampau, dengan warna monokrom.
Saya melihat foto-foto itu dengan tertarik, sambil mengingat-ingat suasana Pekalongan masa lalu yang masih terekam dalam memori. Sebagian tempat dalam foto bisa saya kenali, namun sebagian lain tidak. Kenyataannya, memang, Pekalongan saat ini telah jauh berubah dibanding Pekalongan zaman dulu.
Di salah satu foto yang saya lihat, ada gedung yang berdiri di belakang sebuah jembatan. Ingatan saya langsung memberitahu, itu gedung Bioskop X, yang terakhir kali saya lihat ketika terbakar. Secara spontan, saya pun mengatakan bahwa saya mengenali gedung itu sebagai Bioskop X.
“Gedung bioskop ini sekarang sudah tidak ada,” ujar saya waktu itu. “Tapi dulu aku sempat melihatnya.”
Dia memastikan, “Kamu melihat gedung bioskop ini?”
“Ya, aku melihatnya,” saya menjawab yakin.
Lalu dia menunjuk tahun yang tercetak pada foto—sebuah tulisan kecil yang mendokumentasikan kapan foto itu dibuat. Tahun 1977. Lalu dia berkata, “Kamu pasti belum lahir waktu itu.”
Ya, saya memang belum lahir waktu itu—1977, ketika foto gedung bioskop itu dibuat. Tetapi, saya melihat keberadaan gedung tersebut, beberapa tahun sebelum hancur karena kebakaran.
Waktu itu, saya sempat berniat menjelaskan, bahwa gedung itu masih berdiri ketika saya telah tumbuh menjadi anak-anak, meski tidak lagi beroperasi sebagai bioskop. Karenanya, saya benar-benar melihat gedung itu di sana, sebagaimana yang saya katakan. Tetapi, waktu itu, dia sudah menatap saya dengan tatapan menuduh, seolah saya telah berbohong kepadanya.
Ini rumit, pikir saya.
Dia bukan orang Pekalongan—tidak menyaksikan seperti apa Pekalongan di masa lampau, seperti yang saya saksikan. Dia tidak tahu bahwa gedung Bioskop X masih berdiri lama setelah tidak lagi beroperasi, sampai kemudian terbakar hingga rata dengan tanah. Sebenarnya, dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang Pekalongan, selain dokumentasi yang ia lihat dalam foto.
Karenanya, kalau pun saya berusaha menjelaskan hal tersebut, belum tentu dia akan percaya. Lagi pula, saya juga tidak punya bukti bahwa saya benar-benar menyaksikan gedung itu, selain ingatan semata.
Akhirnya, saya memilih diam, dan membiarkan dia mengira saya berbohong, meski kenyataannya saya tidak berbohong. Dia berpikir sebagaimana umumnya orang lain berpikir—linear, dan mengabaikan detail.
Dalam pikirannya, Bioskop X eksis pada 1970-an, dan waktu itu saya belum lahir. Akhir 1970-an, Bioskop X sudah tidak ada. Saya lahir setelah itu. Jika saya mengatakan bahwa dulu melihat Bioskop X, artinya saya bohong. Itu, baginya, pola pikir yang masuk akal, bahkan sulit digugat. Benar-benar pola pikir yang sangat linear, dan mengabaikan detail—khas orang kebanyakan.
Padahal, realitas kehidupan—dalam banyak hal—tidak selinear itu. Dalam banyak hal, khususnya dalam hal-hal besar, sering kali ada detail-detail yang perlu kita perhatikan, bahkan perlu kita pelajari, agar pemahaman kita benar-benar utuh dan tidak parsial atau sepotong-sepotong. Setiap peristiwa dibangun di atas detail. Jika kita melewatkan detailnya, kita akan gagal menangkap apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam contoh mudah, seperti cerita di atas, adalah Bioskop X.
Memang benar, Bioskop X ada sebelum saya lahir. Ketika saya lahir, Bioskop X sudah bubar. Jika saya mengatakan pernah melihat Bioskop X, tentu saya bohong, karena bioskop itu sudah bubar, bahkan sebelum saya lahir. Itu pikiran linear yang mengabaikan detail.
Realitasnya, saya benar-benar melihat gedung Bioskop X, karena gedung itu masih berdiri sampai lama, meski bioskopnya sudah tidak lagi beroperasi. Saya telah melihat gedung bioskop itu sejak masih kecil sekali, sampai kemudian melihatnya terbakar dan hancur hingga rata dengan tanah, ketika saya kelas tiga SD.
Dalam teori, saya tidak mungkin melihat Bioskop X, karena bioskop itu sudah bubar sebelum saya lahir. Tetapi, dalam realitas, saya benar-benar melihatnya!
Dalam hidup, kadang ada hal-hal yang kita alami, kemudian kita pahami, tetapi kita kesulitan untuk menjelaskan pada orang lain, karena—jika dipikir secara sederhana atau secara linear—yang kita ceritakan akan sulit dipercaya, atau sulit dipahami. Orang lain belum tentu mengalami yang kita alami. Atau, belum tentu bisa memahami yang kita alami. Karenanya, alih-alih percaya, mereka bisa jadi akan mengira kita berbohong, atau mengada-ada, atau membesar-besarkan.
Kadang, ada teman kita menceritakan orang tuanya kejam, yang memperlakukannya sewenang-wenang, hingga dia mengalami trauma berkepanjangan. Karena kita tidak mengalami yang dialaminya, bisa jadi kita enteng mengatakan, “Ah, orang tua galak itu biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan.”
Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.
Teman kita menceritakan orang tuanya kejam—saya ulangi, kejam. Dia tidak mengatakan orang tuanya galak atau keras. Yang dia katakan adalah “kejam”.
Ada perbedaan yang sangat jelas antara galak atau keras dengan kejam. Teman kita pasti bisa membedakan hal itu, dan dia sengaja menggunakan istilah “kejam” untuk menggambarkan perilaku orang tuanya. Tetapi, karena kita berpikir linear—mungkin karena membayangkan orang tua kita sendiri—kita pun dengan mudah mengasumsikan “kejam” dengan “galak”. Itu benar-benar salah kaprah! Kita hanya melihat gambar besar, tapi melewatkan detail!
Susahnya, seperti itulah cara kebanyakan orang berpikir—menarik simpulan berdasarkan yang dialami sendiri, berpikir linear dengan mengabaikan detail, dan lebih mudah menghakimi daripada berusaha memahami.
Ada pula orang yang mengalami depresi, lalu bermaksud curhat ke temannya, berharap dapat meringankan penderitaan depresi yang ia alami. Bukannya mendengarkan dan berempati, si teman malah memberi nasihat yang sok tahu, “Yang perlu kamu lakukan cukup rajin beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, dan menjalani kehidupan dengan ikhlas. Itulah kunci mengobati depresi.”
Sekali lagi, itu pikiran yang mungkin linear, tapi salah kaprah!
Bagi si teman yang memberi nasihat—dan juga bagi orang lain—nasihat itu mungkin terdengar benar. Tapi belum tentu benar bagi yang mengalami depresi. Karena kenyataan yang ia alami tidak sesederhana itu.
Ada hal-hal yang kita tahu, yang kita alami, yang kita pahami, yang ingin kita katakan pada orang lain, tapi kita kesulitan menjelaskan kepada mereka, karena kemungkinan mereka akan sulit memahami, atau sulit percaya, atau bahkan menuduh kita berbohong, membesar-besarkan, atau mengada-ada.
Empati dan pikiran yang terbuka memang sangat mahal di dunia, hingga tidak setiap orang mampu memilikinya.
Jadi ketawa sendiri membayangkan ada orang mengulik akun-akun medsosku, lalu (mungkin) berpikir, "Bocah ini mungkin menyenangkan. Tapi isi akun medsosnya kok gitu, ya? Aku jadi ragu-ragu mau mempekerjakan dia di perusahaanku."
Lha ya bilang ingin kerja di perusahaanmu juga siapa?
Atau, ada wanita yang mungkin mengoprek blog dan akun Twitter-ku, lalu menggumam, "Cowok ini sepertinya asoy. Tapi kok isi tulisannya kadang ngeri gitu, ya. Mau naksir jadi ragu-ragu."
Lha yang berharap kamu naksir juga siapa? Wong umpama kamu naksir juga belum tentu aku mau.
Sejujurnya, itulah yang menjadikanku tidak terlalu percaya dengan apa pun yang kulihat dan kutemukan di dunia maya, karena serba artifisial. Orang-orang atau pengguna medsos berusaha memoles diri sebaik mungkin, yang bisa jadi bertolak belakang dengan dirinya yang asli dan nyata.
Orang paling nyata di dunia maya adalah orang yang aktif di dunia maya tanpa harapan atau keinginan apa pun, termasuk tanpa keinginan mendapat pekerjaan sampai mendapat pasangan. Saat orang eksis tanpa keinginan atau harapan apa pun, dia benar-benar menampakkan sosok aslinya.
Konon, para HRD atau headhunter mempelajari kepribadian orang (dalam arti dangkal) melalui akun-akun medsos orang bersangkutan. Lucu, kalau dipikir-pikir. Karena, apa iya mereka tidak menyadari dan memikirkan bahwa orang belum tentu menunjukkan dirinya yang asli di media sosial?
"Kenapa kamu tidak punya akun FB?"
"Karena aku malas basa-basi."
"Kenapa kamu tidak punya akun LinkedIn?"
"Karena aku tidak mencari pekerjaan."
"Kenapa kamu punya akun Twitter?"
"Karena aku suka ngoceh sendiri."
"Kenapa kamu punya blog?"
"Karena aku suka menuliskan isi pikiran."
Percaya atau tidak, banyak orang bilang telah mengkhatamkan isi blogku seisi-isinya. Kepada mereka, aku ingin mengatakan, "Aku bukan orang terbaik yang bisa kautemukan. Tapi aku bisa mengatakan kepadamu, bahwa aku benar-benar manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangan."
Ada pepatah lama, "Kalau kau belum pernah tidur dengan seseorang sampai tiga hari, jangan pernah yakin kau telah mengenalnya."
Dan sekarang orang-orang merasa bisa mengenal orang per orang hanya lewat media sosial. Well, bagaimana kalau kita mencoba tidur bersama tiga hari?
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 7 September 2018.
Lha ya bilang ingin kerja di perusahaanmu juga siapa?
Atau, ada wanita yang mungkin mengoprek blog dan akun Twitter-ku, lalu menggumam, "Cowok ini sepertinya asoy. Tapi kok isi tulisannya kadang ngeri gitu, ya. Mau naksir jadi ragu-ragu."
Lha yang berharap kamu naksir juga siapa? Wong umpama kamu naksir juga belum tentu aku mau.
Sejujurnya, itulah yang menjadikanku tidak terlalu percaya dengan apa pun yang kulihat dan kutemukan di dunia maya, karena serba artifisial. Orang-orang atau pengguna medsos berusaha memoles diri sebaik mungkin, yang bisa jadi bertolak belakang dengan dirinya yang asli dan nyata.
Orang paling nyata di dunia maya adalah orang yang aktif di dunia maya tanpa harapan atau keinginan apa pun, termasuk tanpa keinginan mendapat pekerjaan sampai mendapat pasangan. Saat orang eksis tanpa keinginan atau harapan apa pun, dia benar-benar menampakkan sosok aslinya.
Konon, para HRD atau headhunter mempelajari kepribadian orang (dalam arti dangkal) melalui akun-akun medsos orang bersangkutan. Lucu, kalau dipikir-pikir. Karena, apa iya mereka tidak menyadari dan memikirkan bahwa orang belum tentu menunjukkan dirinya yang asli di media sosial?
"Kenapa kamu tidak punya akun FB?"
"Karena aku malas basa-basi."
"Kenapa kamu tidak punya akun LinkedIn?"
"Karena aku tidak mencari pekerjaan."
"Kenapa kamu punya akun Twitter?"
"Karena aku suka ngoceh sendiri."
"Kenapa kamu punya blog?"
"Karena aku suka menuliskan isi pikiran."
Percaya atau tidak, banyak orang bilang telah mengkhatamkan isi blogku seisi-isinya. Kepada mereka, aku ingin mengatakan, "Aku bukan orang terbaik yang bisa kautemukan. Tapi aku bisa mengatakan kepadamu, bahwa aku benar-benar manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangan."
Ada pepatah lama, "Kalau kau belum pernah tidur dengan seseorang sampai tiga hari, jangan pernah yakin kau telah mengenalnya."
Dan sekarang orang-orang merasa bisa mengenal orang per orang hanya lewat media sosial. Well, bagaimana kalau kita mencoba tidur bersama tiga hari?
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 7 September 2018.
Semakin ke puncak, jumlah oksigen semakin menipis.
Orang tak bisa lama-lama di puncak. Kapan pun waktunya
harus turun. Untuk tetap hidup.
Francys dan Sergei Arsentiev adalah pasangan suami istri berdarah Rusia. Mereka pasangan yang cocok, dan sama-sama suka berpetualang, khususnya mendaki gunung.
Dua puluh tahun yang lalu, pada Mei 1998, Francys dan Sergei memutuskan untuk mendaki Everest. Itu merupakan pendakian mereka yang ketiga, setelah dua pendakian sebelumnya gagal. Dalam pendakian kali ini, mereka tidak membawa tabung oksigen, karena mungkin berpikir sudah mengenali medan di Everest dari pendakian sebelumnya.
Seperti kita tahu, Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Gunung itu memiliki ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, atau sekitar 29.029 kaki. Dengan ketinggian itu, Everest sudah pasti berselimut salju abadi. Jika mendaki ke sana, kita akan merasakan oksigen semakin menipis seiring makin tinggi tempat yang didaki. Karenanya, para pendaki Everest selalu melengkapi diri dengan tabung oksigen, yang merupakan “nyawa kedua” begitu mulai mendaki puncak.
Selain Francys dan Sergei Arsentiev, ada banyak pendaki lain yang juga sama-sama bermimpi menaklukkan puncak Everest. Di sana, pasangan suami istri itu saling sapa dengan mereka, dan mula-mula tidak ada masalah.
Tapi Everest tidak seindah yang tampak di foto-foto. Di balik keindahannya yang memukau, Everest sebenarnya kuburan massal raksasa. Tak terhitung banyaknya orang tewas di sana dengan berbagai sebab—kebanyakan karena kedinginan—dan jasad-jasad mereka tersebar di mana-mana. Karena cuaca yang sangat dingin, tubuh-tubuh mereka bisa dibilang masih utuh, meski telah mati bertahun-tahun.
Mayat-mayat yang berserak di sana sudah menjadi pemandangan umum para pendaki Everest. Mayat-mayat itu juga seperti peringatan keras yang memberitahu, bahwa siapa pun bisa bernasib sama. Sepanjang perjalanan menuju ke puncak Everest, yang ada hanya lapisan salju, cuaca yang dingin menggigit, medan yang curam dan berbahaya, serta badai yang bisa datang sewaktu-waktu.
Badai itu juga muncul ketika pasangan Francys dan Sergei sedang di tengah pendakian. Pada 23 Mei 1998, di tengah cuaca yang dingin menggigit tulang, badai menyergap dengan kencang. Francys dan Sergei—juga para pendaki lain—tercerai-berai, masing-masing berusaha menemukan tempat berlindung, dan Francys mendapati dirinya terpisah dengan Sergei.
Seusai badai reda, Sergei menemui pendaki lain, dan meminta bantuan oksigen serta obat-obatan. Setelah itu, dia berusaha mencari istrinya di hamparan luas bersalju dingin membeku.
Di sisi lain, Francys menderita kedinginan dan kelelahan. Ketika badai menerjang, tubuhnya terlempar ke suatu tempat, lalu terperosok ke sisi tebing, dan tergeletak tak berdaya di hamparan salju. Dengan mata yang mulai mengabur, Francys berteriak minta tolong, dengan suara yang serak... dengan napas yang makin berat.
Teriakan serak Francys terdengar oleh dua pendaki, pasangan Woodall dan Cathy O’Dowd, pada pagi 24 Mei 1998. Menurut Woodall dan Cathy, saat itu Francys terkapar, dan berkata sambil menangis, “Please, don’t leave me. Don’t leave me here to die.”
Apa yang sekiranya akan kaulakukan, ketika mendapati seorang wanita terkapar tak berdaya, sekarat, dan meminta pertolonganmu sambil berurai air mata? Di tempat lain, mungkin langkah yang tepat adalah menggotong atau menggendongnya, membawa ke tempat yang lebih baik, kemudian menghubungi rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Tapi ini Everest!
Kalau kau berada di Everest, dan sekarat, kau tidak bisa mengharapkan apa pun, selain hanya menunggu ajal datang menjemput. Para pendaki di sana sudah “tahu sama tahu” bahwa kalau kau tidak sanggup berdiri, artinya kau akan mati.
Hal itu pula yang dipikirkan Woodall dan Cathy O’Dowd, ketika mendapati Francys terkapar dan sekarat. Mereka tahu tidak mungkin bisa menolong Francys. Akhirnya, mereka hanya bisa memberikan bantuan oksigen, dan berharap—entah bagaimana caranya—Francys bisa pulih dari kondisinya yang sekarat. Tapi mereka tahu, itu harapan sia-sia. Di hadapan mereka, tubuh Francys tampak makin melemah, hingga akhirnya meninggal.
Lalu bagaimana dengan Sergei, sang suami? Sayang, dia juga mengalami nasib sama. Bersama oksigen yang makin menipis, Sergei kehabisan napas, terperosok, dan meninggal, sama seperti istrinya.
Delapan tahun kemudian, Woodall dan Cathy O’Dowd kembali ke Everest dan mendatangi tempat jasad Francys berada. Semula, mereka bermaksud memberi pemakaman yang layak untuk Francys. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka hanya bisa menutupi jasad Francys dengan kain bendera, dan menyelipkan sepucuk surat yang dititipkan keluarga Francys.
Masyarakat India mengeramatkan Everest, karena menganggap gunung itu sebagai tempat suci. Sementara penduduk Tibet menyebut Everest dengan nama Qomolangma, yang berarti Ibu Alam Semesta. Dengan ketinggiannya yang luar biasa, Everest adalah tempat yang paling dekat ke langit, sekaligus atap tertinggi bumi. Karenanya, banyak orang—khususnya para pendaki—ingin menaklukkan puncak Everest, karena itu sama artinya berdiri di puncak dunia.
Tetapi, sekali lagi, Everest tidak seindah yang kita saksikan di gambar. Di balik wajahnya yang tampak “tanpa dosa”, Everest adalah jebakan maut yang menantang ego siapa pun yang ingin menaklukkannya. Dan ada banyak orang terjebak di sana, bermimpi dapat mencapai puncak, tapi kemudian membeku menjadi mayat. Di antara segelintir orang yang berhasil sampai puncak, ada ribuan yang gagal.
Tapi sejarah tak mencatat orang-orang gagal. Sejarah hanya mencatat para pemenang. Sejarah tak peduli pada mayat-mayat yang berserakan di lereng, di lembah, di tebing, dan di mana pun di Everest. Sejarah hanya mencatat pemenang, nama yang berhasil menaklukkan puncak, yang hanya segelintir. Di antara ribuan yang datang, hanya beberapa yang menang.
Maka dunia pun menatapkan pandangan pada sang pemenang, dan orang-orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal serupa. Mereka tidak pernah diberitahu banyak mayat yang telah terkapar di Everest, mereka hanya diberitahu siapa yang berhasil sampai puncak. Mereka tidak belajar pada yang gagal, mereka hanya belajar pada yang berhasil. Padahal, kesadaran untuk bisa gagal sama penting dengan keinginan untuk berhasil.
Tapi manusia tampaknya memang sulit untuk menyadari realitas, dan enggan menerima kebenaran berdasarkan kenyataan. Ketika menatap puncak Everest, yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang telah berhasil sampai puncak, dan sama sekali tak menghiraukan mayat-mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Mereka berpikir untuk sampai di puncak, tapi melupakan kemungkinan bahwa mereka juga bisa menjadi mayat yang ikut berserak.
Mencapai puncak adalah impian setiap orang; dari puncak Everest sampai puncak kehidupan. Tetapi, menyadari realitas sebelum sampai di puncak adalah bagian pembelajaran yang perlu dipahami. Bahwa ada kemungkinan berhasil, namun juga ada kemungkinan gagal. Pemahaman itu diperlukan, agar kita mempersiapkan diri lebih baik, untuk menimimalkan kemungkinan gagal dan memperbesar kemungkinan berhasil.
Francys dan Sergei Arsentiev mungkin tidak sempat memikirkan hal itu. Mereka sudah dua kali datang ke Everest, dan menyaksikan langsung seperti apa medan di sana, serta mayat-mayat yang berserakan di sepanjang jalan. Tetapi, alih-alih menyadari bahwa mereka juga bisa menjadi mayat di sana, Francys dan Sergei justru hanya menujukan tatapan ke puncak. Akibatnya, mereka kurang persiapan. Ketika datang ke sana untuk ketiga kali, mereka tidak membawa tabung oksigen dan perlengkapan yang memadai.
Optimisme itu penting. Tapi mempersiapkan diri tak kalah penting. Karena di saat sekarat, maut tak peduli kau optimis atau tidak. Francys dan Sergei pasti pasangan yang sangat optimis. Sebegitu optimis, sampai mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik. Realitas akhirnya datang dalam wujud badai, dan optimisme terbukti tak banyak menolong. Mereka tercerai berai, dan sekarat, dan mati.
Menggapai puncak adalah impian indah. Bayangan itu serupa dengan pikiran kebanyakan kita terhadap perkawinan, atau pencapaian lain. Semua orang menujukan khayal pada pelaminan, pada keindahan, tapi melupakan kemungkinan yang bisa terjadi dalam perjalanan menuju ke sana. Padahal, pernikahan serupa Everest—indah dalam foto-foto, bahkan indah saat diceritakan, tapi bisa mengerikan dalam realitas.
Dan sama seperti para pendaki Everest yang tidak menghiraukan mayat-mayat berserakan di sana, kebanyakan kita juga sama tak menghiraukan berapa banyak orang yang bercerai, rumah tangga yang berantakan, keluarga yang kacau dan rusak, hingga anak-anak yang telantar. Karena kita hanya menujukan pandangan kepada puncak, kepada khayal, kepada impian perkawinan sempurna.
Padahal, di balik hal-hal yang tampak sempurna... selalu ada jerit sunyi yang tak pernah kita dengar.
Ada banyak hal yang ingin kutulis di blog, sebagaimana misi awal menulis di blog sebagai upaya "mewaraskan pikiran". Namun, seiring perjalanan waktu, ada banyak hal yang terjadi. Dua kendala yang paling terasa: makin sedikitnya waktu, dan makin rumitnya hal yang ingin kutulis.
Dulu, di catatan ini » http://bit.ly/2hpek37 aku pernah menjanjikan untuk menulis lanjutannya. Belakangan, aku "ngeri" jika harus menulisnya, karena mengkhawatirkan dampak yang mungkin terjadi. Bagi diriku sendiri, maupun bagi orang lain yang membaca.
Jika aku harus menulis lanjutan catatan tersebut, aku harus menabrak sekaligus meruntuhkan banyak hal terkait keyakinan banyak orang, lalu "mengorek-ngorek" sedemikian gila, untuk kemudian menyuguhkan fakta yang sebenarnya. Meski yang kutulis bisa dibuktikan, tapi itu mengerikan.
Terkait manusia, aku percaya kepada satu kebenaran: Tidak setiap manusia siap menghadapi dan menerima kebenaran. Karena, kenyataannya, manusia tidak percaya kebenaran. Mereka hanya percaya pada sesuatu yang mereka anggap (yakini, percaya, harapkan) sebagai kebenaran.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 13 Juni 2018.
Dulu, di catatan ini » http://bit.ly/2hpek37 aku pernah menjanjikan untuk menulis lanjutannya. Belakangan, aku "ngeri" jika harus menulisnya, karena mengkhawatirkan dampak yang mungkin terjadi. Bagi diriku sendiri, maupun bagi orang lain yang membaca.
Jika aku harus menulis lanjutan catatan tersebut, aku harus menabrak sekaligus meruntuhkan banyak hal terkait keyakinan banyak orang, lalu "mengorek-ngorek" sedemikian gila, untuk kemudian menyuguhkan fakta yang sebenarnya. Meski yang kutulis bisa dibuktikan, tapi itu mengerikan.
Terkait manusia, aku percaya kepada satu kebenaran: Tidak setiap manusia siap menghadapi dan menerima kebenaran. Karena, kenyataannya, manusia tidak percaya kebenaran. Mereka hanya percaya pada sesuatu yang mereka anggap (yakini, percaya, harapkan) sebagai kebenaran.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 13 Juni 2018.
Ini kisah gila, dan sebaiknya jangan ditiru. Bahkan, sebaiknya, jangan sampai mengalami yang saya alami.
Sebelumnya, saya ingin jujur mengatakan—dan tolong maafkan kalau terlalu blak-blakan—saya benci rumah sakit! Maksud saya, sangat... benci... rumah sakit.
Berdasarkan pengalaman, sepertinya tidak ada hal menarik di rumah sakit. Tempat itu identik dengan sakit, penyakit, kesakitan, obat-obatan yang sangat tidak enak, makanan yang sama tidak enak, serta suasana yang—bagi saya—seperti horor mencekam. Berdasarkan pengalaman, belum pernah saya masuk rumah sakit dan merasa nyaman, lalu betah tinggal di dalamnya. Setiap kali terpaksa masuk rumah sakit, saya selalu ingin segera minggat dari sana.
Sebagai bocah, saya tahu betul, seenak-enaknya tidur di rumah sakit, masih lebih enak tidur di hotel! (Ya iyalah, bangsat!)
Well, salah satu pengalaman saya dengan rumah sakit, terjadi saat saya mengalami kecelakaan parah, yang diceritakan di sini. Waktu itu, selain tubuh penuh luka, tangan kanan saya patah. Saya digotong beberapa orang dari jalan raya, dan dibaringkan di trotoar.
Orang-orang mengerumuni saya—sang korban kecelakaan—tapi mereka tampak kebingungan, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mereka “terpesona” melihat luka-luka yang saya alami, atau mereka memang bangsat-bangsat yang tak peduli korban kecelakaan, selain hanya ingin menonton.
Antara sadar dan tak sadar, saya berpikir cepat mengenai apa yang harus saya lakukan, sebelum benar-benar pingsan. Dalam kondisi yang amat kritis itu, saya ingat, teman yang paling dekat dari lokasi kecelakaan—dan bisa ditelepon—adalah Alkaf. Jadi, dengan susah payah dan kesakitan, saya merogoh saku celana, dan mengambil ponsel.
Dengan mata nanar nyaris tak sadar, saya menggulir phonebook di ponsel, hingga menemukan nama Alkaf (untung nama dia diawali huruf A). Setelah telepon tersambung, saya bilang kepadanya, bahwa saya mengalami kecelakaan, menyebut tempat kejadian, dan meminta tolong.
Setelah itu, saya pingsan.
Saya mulai sadar dari pingsan, saat telah ada di mobil Alkaf, yang melaju entah ke mana. Pada waktu itulah, saya mulai merasakan sakit luar biasa, dari bagian tangan kanan yang patah. Suakitnya tidak bisa dijelaskan kata-kata.
Menurut Alkaf, yang terus menyetir, kami sedang menuju rumah sakit yang paling dekat. Tetapi bahkan yang “paling dekat” itu pun rasanya jauh sekali, tak sampai-sampai, sementara sakit yang saya rasakan semakin tak karuan. Itu menjadi saat-saat paling menyiksa dalam hidup yang pernah saya alami.
Ketika akhirnya kami sampai di rumah sakit, saya dimasukkan ke sebuah kamar—yang mungkin—khusus untuk korban kecelakaan. Setelah melihat saya ditangani perawat di rumah sakit, Alkaf pergi. Dia perlu mengabari orang tua saya.
Dan selanjutnya adalah serangkaian kisah gila.
Saya tidak ingat, berapa hari atau berapa abad saya harus dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan itu, yang jelas rasanya lama sekali. Setelah mendapat pertolongan awal, saya ditempatkan di kamar lain, bersebelahan dengan seorang laki-laki yang mengalami patah tulang punggung.
Jadi, di kamar itu hanya terdapat dua ranjang atau tempat tidur untuk pasien. Ketika orang tua saya datang ke rumah sakit, ibu saya memutuskan untuk menginap, berjaga-jaga kalau saya butuh sesuatu. Saya tidur di ranjang, ibu tidur di sofa yang ada di depan ranjang.
Di sebelah saya, ada satu ranjang lain, yang ditempati laki-laki tadi—yang mengalami patah tulang punggung. Laki-laki itu mungkin berusia 50-an, dan dia ditemani istrinya, yang juga tidur di sofa kamar.
Berdasarkan percakapan ibu saya dengan istri si laki-laki, ternyata laki-laki itu terjatuh dari ketinggian, hingga punggungnya patah. Dia harus menjalani operasi beberapa kali, dan proses pemindahan dia dari ranjangnya ke kereta dorong—untuk menuju ruang operasi—adalah saat-saat paling menegangkan yang pernah saya saksikan. Dari ranjang ke kereta dorong, dia harus digotong beberapa orang, dan proses pemindahan itu adalah kesakitan luar biasa yang harus dialami si laki-laki, mengingat tulang punggungnya patah.
Saya bisa membayangkan kesakitan yang ia derita. Wong saya “cuma” patah tulang tangan saja rasanya sakit luar biasa, apalagi dia? Jadi, selama tinggal di kamar itu pula, saya harus membiasakan diri mendengarkan rintih kesakitan dari ranjang sebelah, yang nyaris tanpa henti. Sebenarnya, saya juga ingin merintih, akibat sakit yang juga saya alami. Tapi saya malu. Mosok patah tulang tangan saja harus ikut-ikutan merintih?
....
Sebelumnya, saya ingin jujur mengatakan—dan tolong maafkan kalau terlalu blak-blakan—saya benci rumah sakit! Maksud saya, sangat... benci... rumah sakit.
Berdasarkan pengalaman, sepertinya tidak ada hal menarik di rumah sakit. Tempat itu identik dengan sakit, penyakit, kesakitan, obat-obatan yang sangat tidak enak, makanan yang sama tidak enak, serta suasana yang—bagi saya—seperti horor mencekam. Berdasarkan pengalaman, belum pernah saya masuk rumah sakit dan merasa nyaman, lalu betah tinggal di dalamnya. Setiap kali terpaksa masuk rumah sakit, saya selalu ingin segera minggat dari sana.
Sebagai bocah, saya tahu betul, seenak-enaknya tidur di rumah sakit, masih lebih enak tidur di hotel! (Ya iyalah, bangsat!)
Well, salah satu pengalaman saya dengan rumah sakit, terjadi saat saya mengalami kecelakaan parah, yang diceritakan di sini. Waktu itu, selain tubuh penuh luka, tangan kanan saya patah. Saya digotong beberapa orang dari jalan raya, dan dibaringkan di trotoar.
Orang-orang mengerumuni saya—sang korban kecelakaan—tapi mereka tampak kebingungan, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mereka “terpesona” melihat luka-luka yang saya alami, atau mereka memang bangsat-bangsat yang tak peduli korban kecelakaan, selain hanya ingin menonton.
Antara sadar dan tak sadar, saya berpikir cepat mengenai apa yang harus saya lakukan, sebelum benar-benar pingsan. Dalam kondisi yang amat kritis itu, saya ingat, teman yang paling dekat dari lokasi kecelakaan—dan bisa ditelepon—adalah Alkaf. Jadi, dengan susah payah dan kesakitan, saya merogoh saku celana, dan mengambil ponsel.
Dengan mata nanar nyaris tak sadar, saya menggulir phonebook di ponsel, hingga menemukan nama Alkaf (untung nama dia diawali huruf A). Setelah telepon tersambung, saya bilang kepadanya, bahwa saya mengalami kecelakaan, menyebut tempat kejadian, dan meminta tolong.
Setelah itu, saya pingsan.
Saya mulai sadar dari pingsan, saat telah ada di mobil Alkaf, yang melaju entah ke mana. Pada waktu itulah, saya mulai merasakan sakit luar biasa, dari bagian tangan kanan yang patah. Suakitnya tidak bisa dijelaskan kata-kata.
Menurut Alkaf, yang terus menyetir, kami sedang menuju rumah sakit yang paling dekat. Tetapi bahkan yang “paling dekat” itu pun rasanya jauh sekali, tak sampai-sampai, sementara sakit yang saya rasakan semakin tak karuan. Itu menjadi saat-saat paling menyiksa dalam hidup yang pernah saya alami.
Ketika akhirnya kami sampai di rumah sakit, saya dimasukkan ke sebuah kamar—yang mungkin—khusus untuk korban kecelakaan. Setelah melihat saya ditangani perawat di rumah sakit, Alkaf pergi. Dia perlu mengabari orang tua saya.
Dan selanjutnya adalah serangkaian kisah gila.
Saya tidak ingat, berapa hari atau berapa abad saya harus dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan itu, yang jelas rasanya lama sekali. Setelah mendapat pertolongan awal, saya ditempatkan di kamar lain, bersebelahan dengan seorang laki-laki yang mengalami patah tulang punggung.
Jadi, di kamar itu hanya terdapat dua ranjang atau tempat tidur untuk pasien. Ketika orang tua saya datang ke rumah sakit, ibu saya memutuskan untuk menginap, berjaga-jaga kalau saya butuh sesuatu. Saya tidur di ranjang, ibu tidur di sofa yang ada di depan ranjang.
Di sebelah saya, ada satu ranjang lain, yang ditempati laki-laki tadi—yang mengalami patah tulang punggung. Laki-laki itu mungkin berusia 50-an, dan dia ditemani istrinya, yang juga tidur di sofa kamar.
Berdasarkan percakapan ibu saya dengan istri si laki-laki, ternyata laki-laki itu terjatuh dari ketinggian, hingga punggungnya patah. Dia harus menjalani operasi beberapa kali, dan proses pemindahan dia dari ranjangnya ke kereta dorong—untuk menuju ruang operasi—adalah saat-saat paling menegangkan yang pernah saya saksikan. Dari ranjang ke kereta dorong, dia harus digotong beberapa orang, dan proses pemindahan itu adalah kesakitan luar biasa yang harus dialami si laki-laki, mengingat tulang punggungnya patah.
Saya bisa membayangkan kesakitan yang ia derita. Wong saya “cuma” patah tulang tangan saja rasanya sakit luar biasa, apalagi dia? Jadi, selama tinggal di kamar itu pula, saya harus membiasakan diri mendengarkan rintih kesakitan dari ranjang sebelah, yang nyaris tanpa henti. Sebenarnya, saya juga ingin merintih, akibat sakit yang juga saya alami. Tapi saya malu. Mosok patah tulang tangan saja harus ikut-ikutan merintih?
....
....
Kegiatan saya selama di rumah sakit adalah tanpa kegiatan sama sekali. Lha piye? Sekujur tubuh penuh luka. Tangan kanan—yang mengalami patah tulang—dipasangi papan yang menjadikan tangan saya mirip robot, dan berat untuk digerakkan. Tangan kiri ditancapi jarum infus, sementara dua kaki terasa kaku akibat luka-luka.
Saya tidak bisa apa-apa, selain hanya berbaring. Dan berbaring. Dan berbaring. Dan berbaring. Benar-benar kegiatan yang tidak enviromental, tidak quo vadis, dan tidak moratorium—apa pun artinya.
Setiap hari, ada perawat atau dokter yang datang menjenguk, entah untuk mengecek botol infus, atau untuk hal lain. Mereka juga memberikan sepaket pil aneka warna yang sekilas mirip gula-gula, tapi perasaan saya tidak enak setiap kali melihatnya. Dokter mengatakan agar saya minum dua butir siang hari, dan dua butir lagi sore hari. Paket pil itu diletakkan di meja samping ranjang, tapi tidak saya sentuh sama sekali.
Suatu kali, dokter datang, dan melihat paket pil itu masih utuh. Dia menanyakan hal itu, dan meminta saya mengonsumsi obat yang ia berikan. “Ini membantu mengurangi sakit, sekaligus mempercepat kesembuhan.”
Dengan lugu, saya bertanya, “Apakah pil-pil ini pahit, Dok?”
Dia tersenyum, dan menyahut, “Namanya juga obat, Mas. Tentu pahit.”
Saya menjelaskan, “Itulah masalahnya. Saya tidak bisa menelan pil.”
Dia menatap bingung, seolah saya tiba-tiba gegar otak. “Jadi?”
“Jadi, saya harus mengunyahnya. Karena itulah, saya ngeri kalau rasanya pahit. Saya khawatir nanti muntah tak karuan. Bisa-bisa bukannya sembuh, sakit saya makin parah.”
Dokter itu tampak bingung, dan saya benar-benar penasaran apa yang dipikirkannya saat itu. Tapi dia tidak ngomong apa-apa, selain hanya tersenyum sekilas. Benar-benar dokter yang simpatik.
....
Kegiatan saya selama di rumah sakit adalah tanpa kegiatan sama sekali. Lha piye? Sekujur tubuh penuh luka. Tangan kanan—yang mengalami patah tulang—dipasangi papan yang menjadikan tangan saya mirip robot, dan berat untuk digerakkan. Tangan kiri ditancapi jarum infus, sementara dua kaki terasa kaku akibat luka-luka.
Saya tidak bisa apa-apa, selain hanya berbaring. Dan berbaring. Dan berbaring. Dan berbaring. Benar-benar kegiatan yang tidak enviromental, tidak quo vadis, dan tidak moratorium—apa pun artinya.
Setiap hari, ada perawat atau dokter yang datang menjenguk, entah untuk mengecek botol infus, atau untuk hal lain. Mereka juga memberikan sepaket pil aneka warna yang sekilas mirip gula-gula, tapi perasaan saya tidak enak setiap kali melihatnya. Dokter mengatakan agar saya minum dua butir siang hari, dan dua butir lagi sore hari. Paket pil itu diletakkan di meja samping ranjang, tapi tidak saya sentuh sama sekali.
Suatu kali, dokter datang, dan melihat paket pil itu masih utuh. Dia menanyakan hal itu, dan meminta saya mengonsumsi obat yang ia berikan. “Ini membantu mengurangi sakit, sekaligus mempercepat kesembuhan.”
Dengan lugu, saya bertanya, “Apakah pil-pil ini pahit, Dok?”
Dia tersenyum, dan menyahut, “Namanya juga obat, Mas. Tentu pahit.”
Saya menjelaskan, “Itulah masalahnya. Saya tidak bisa menelan pil.”
Dia menatap bingung, seolah saya tiba-tiba gegar otak. “Jadi?”
“Jadi, saya harus mengunyahnya. Karena itulah, saya ngeri kalau rasanya pahit. Saya khawatir nanti muntah tak karuan. Bisa-bisa bukannya sembuh, sakit saya makin parah.”
Dokter itu tampak bingung, dan saya benar-benar penasaran apa yang dipikirkannya saat itu. Tapi dia tidak ngomong apa-apa, selain hanya tersenyum sekilas. Benar-benar dokter yang simpatik.
....
....
Saat-saat di rumah sakit adalah saat-saat yang sangat membosankan, karena saya benar-benar tidak bisa apa-apa selain berbaring, sakit, berbaring, gelisah, berbaring, menatap langit-langit kamar, berbaring... dan mungkin begitu terus sampai kiamat.
Untung, selama menjalani masa-masa yang menyiksa itu, ada banyak teman berdatangan. Melihat mereka, bercakap-cakap, dan menikmati canda tawa mereka, cukup mengobati sakit yang saya rasakan. Karenanya, saat mereka harus pergi karena jam berkunjung sudah habis, saya merasa ingin menangis.
Waktu itu, di antara teman dekat saya adalah Alkaf dan Yusron (biasa dipanggil Achong). Hampir saban hari, dua bocah itu menjenguk ke rumah sakit—hanya berdua, maupun bersama teman-teman yang lain.
Suatu sore, mereka berdua datang berkunjung seperti biasa. Kami mengobrol di kamar tempat saya berbaring. Waktu itu, tubuh saya sudah agak kuat, sehingga mampu berdiri dan berjalan. Tapi karena ada infus keparat yang ditancapkan ke tangan saya, terpaksa saya tidak bisa ke mana-mana.
Achong bertanya, apa yang saya inginkan waktu itu. Dengan jujur, saya menjawab, “Aku ingin merokok.”
Waktu itu, karena menjadi pasien di rumah sakit, saya sudah tidak merokok beberapa hari—atau beberapa abad—dan saya benar-benar ingin merokok. Tapi saya tidak mungkin merokok di kamar perawatan. Sementara saya juga tidak mungkin keluyuran sendirian. Namanya juga orang sakit!
Menyadari saya benar-benar ingin merokok, Alkaf lalu keluar kamar, untuk mencari tempat “strategis” yang sekiranya bisa digunakan. Beberapa saat kemudian dia kembali, dan membawa kabar gembira.
Tidak jauh dari kamar saya, ada tempat yang tampaknya ditujukan untuk keluarga pasien yang ingin mencuci atau bersih-bersih. Tempat itu tak beratap, sehingga langit dapat terlihat. Menurut Alkaf, tempat itu sepi, dan tampaknya saya bisa merokok di sana. Saya pun langsung setuju. Well, apa pilihan saya?
Saya bangkit dari ranjang. Achong memegangi botol infus, sementara Alkaf membantu menahan tangan saya yang dibalut papan, yang berat mirip robot. Lalu perlahan kami melangkah ke tempat yang ditunjuk Alkaf. Di sana memang sepi.
Kami berdiri bersisian di sana, dengan Achong yang masih memegangi botol infus, dan Alkaf memegangi tangan robot saya. Alkaf mengambil rokok, meletakkan sebatang di mulut saya, menyulutnya, dan saya mengisap perlahan. Waktu itu, kedua tangan saya tidak bisa digunakan. Jadi, Alkaf melepaskan rokok dari mulut saya setelah saya mengisap, dan kembali meletakkan di mulut saya, menunggu saya mengisap lagi, dan begitu seterusnya.
Subhanallah... itu benar-benar saat merokok paling nikmat yang pernah saya rasakan.
Setelah beberapa hari—atau beberapa abad—hanya terbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak, dan setelah lama menahan mulut yang asem ingin merokok, moment itu benar-benar menjadi saat yang sangat indah.
Sejak itu, seiring tubuh makin kuat, dan tangan kiri saya mulai bisa digerakkan, saya pun kadang curi-curi waktu dengan pergi ke sana untuk merokok sendirian. Untuk memuluskan “petualangan” itu, saya meminjam kursi roda milik pasien sebelah saya.
Pasien sebelah saya—laki-laki yang patah tulang punggung—membutuhkan kursi roda untuk keluar kamar. Karena itu, ada kursi roda khusus yang disediakan untuknya, lengkap dengan tiang untuk meletakkan botol infus. Jika saya ingin merokok, dan kursi roda itu tidak dipakai, saya meminjam kursi roda tersebut. Saya pindahkan botol infus ke tiang di kursi roda, lalu duduk dan membawanya ke tempat sepi untuk merokok. Itu, sekali lagi, menjadi moment-moment indah yang sulit saya lupakan.
Yang paling mengesankan dari kisah ini adalah... ndilalah saya tidak pernah “konangan” setiap kali merokok di sana. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau sewaktu-waktu saya ketahuan merokok di rumah sakit. Kalau dihukum push up, bisa modar saya!
Jadi, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah gila ini?
Jangan merokok? Bukan!
Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah... jangan kecelakaan!
Saat-saat di rumah sakit adalah saat-saat yang sangat membosankan, karena saya benar-benar tidak bisa apa-apa selain berbaring, sakit, berbaring, gelisah, berbaring, menatap langit-langit kamar, berbaring... dan mungkin begitu terus sampai kiamat.
Untung, selama menjalani masa-masa yang menyiksa itu, ada banyak teman berdatangan. Melihat mereka, bercakap-cakap, dan menikmati canda tawa mereka, cukup mengobati sakit yang saya rasakan. Karenanya, saat mereka harus pergi karena jam berkunjung sudah habis, saya merasa ingin menangis.
Waktu itu, di antara teman dekat saya adalah Alkaf dan Yusron (biasa dipanggil Achong). Hampir saban hari, dua bocah itu menjenguk ke rumah sakit—hanya berdua, maupun bersama teman-teman yang lain.
Suatu sore, mereka berdua datang berkunjung seperti biasa. Kami mengobrol di kamar tempat saya berbaring. Waktu itu, tubuh saya sudah agak kuat, sehingga mampu berdiri dan berjalan. Tapi karena ada infus keparat yang ditancapkan ke tangan saya, terpaksa saya tidak bisa ke mana-mana.
Achong bertanya, apa yang saya inginkan waktu itu. Dengan jujur, saya menjawab, “Aku ingin merokok.”
Waktu itu, karena menjadi pasien di rumah sakit, saya sudah tidak merokok beberapa hari—atau beberapa abad—dan saya benar-benar ingin merokok. Tapi saya tidak mungkin merokok di kamar perawatan. Sementara saya juga tidak mungkin keluyuran sendirian. Namanya juga orang sakit!
Menyadari saya benar-benar ingin merokok, Alkaf lalu keluar kamar, untuk mencari tempat “strategis” yang sekiranya bisa digunakan. Beberapa saat kemudian dia kembali, dan membawa kabar gembira.
Tidak jauh dari kamar saya, ada tempat yang tampaknya ditujukan untuk keluarga pasien yang ingin mencuci atau bersih-bersih. Tempat itu tak beratap, sehingga langit dapat terlihat. Menurut Alkaf, tempat itu sepi, dan tampaknya saya bisa merokok di sana. Saya pun langsung setuju. Well, apa pilihan saya?
Saya bangkit dari ranjang. Achong memegangi botol infus, sementara Alkaf membantu menahan tangan saya yang dibalut papan, yang berat mirip robot. Lalu perlahan kami melangkah ke tempat yang ditunjuk Alkaf. Di sana memang sepi.
Kami berdiri bersisian di sana, dengan Achong yang masih memegangi botol infus, dan Alkaf memegangi tangan robot saya. Alkaf mengambil rokok, meletakkan sebatang di mulut saya, menyulutnya, dan saya mengisap perlahan. Waktu itu, kedua tangan saya tidak bisa digunakan. Jadi, Alkaf melepaskan rokok dari mulut saya setelah saya mengisap, dan kembali meletakkan di mulut saya, menunggu saya mengisap lagi, dan begitu seterusnya.
Subhanallah... itu benar-benar saat merokok paling nikmat yang pernah saya rasakan.
Setelah beberapa hari—atau beberapa abad—hanya terbaring di ranjang dan tidak bisa bergerak, dan setelah lama menahan mulut yang asem ingin merokok, moment itu benar-benar menjadi saat yang sangat indah.
Sejak itu, seiring tubuh makin kuat, dan tangan kiri saya mulai bisa digerakkan, saya pun kadang curi-curi waktu dengan pergi ke sana untuk merokok sendirian. Untuk memuluskan “petualangan” itu, saya meminjam kursi roda milik pasien sebelah saya.
Pasien sebelah saya—laki-laki yang patah tulang punggung—membutuhkan kursi roda untuk keluar kamar. Karena itu, ada kursi roda khusus yang disediakan untuknya, lengkap dengan tiang untuk meletakkan botol infus. Jika saya ingin merokok, dan kursi roda itu tidak dipakai, saya meminjam kursi roda tersebut. Saya pindahkan botol infus ke tiang di kursi roda, lalu duduk dan membawanya ke tempat sepi untuk merokok. Itu, sekali lagi, menjadi moment-moment indah yang sulit saya lupakan.
Yang paling mengesankan dari kisah ini adalah... ndilalah saya tidak pernah “konangan” setiap kali merokok di sana. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau sewaktu-waktu saya ketahuan merokok di rumah sakit. Kalau dihukum push up, bisa modar saya!
Jadi, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah gila ini?
Jangan merokok? Bukan!
Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah... jangan kecelakaan!
Dolar AS Tembus Rp 14.800, Masyarakat Diminta
Tidak Khawatir https://bit.ly/2Qi1Ong
—@kumparan
Itu pula yang dulu dikatakan pemerintah Venezuela
kepada rakyatnya. "Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir."
Dan, lihat, apa yang sekarang terjadi di sana?
—@noffret
Venezuela adalah contoh nyata bagaimana utang bisa menjerat dan menghancurkan negara sekaya apa pun. Jangan lupa, Venezuela memiliki sumber minyak, dan menjadi negara terkaya di Amerika Latin. Tapi bahkan negara sekaya itu pun kolaps dan rakyatnya menjadi korban, gara-gara utang.
Bertahun lalu, ketika masih kaya-raya, pemerintah Venezuela biasa mengatakan kepada rakyatnya, "Tidak perlu mengkhawatirkan utang. Kita punya sumber minyak, kita kaya-raya, rasio PDB kita bagus, coba bandingkan negara lain..." Apakah ini terdengar familier? Oh, well, tentu saja.
Kenyataannya, Venezuela memang negara kaya-raya, dan utang mereka tergolong aman jika dibandingkan dengan rasio PDB. Tetapi utang adalah jerat di leher, sementara rasio PDB adalah bangku (kekayaan dan kurs mata uang) yang menahan kakimu. Sudah paham bagaimana cara memainkannya?
Pernahkah kita memikirkan kenyataan yang sangat gamblang ini: Jika sebuah negara kaya-raya, mengapa sampai kolaps terjerat utang?
Apa pun jawaban atas pertanyaan itu akan membawa pada kenyataan bahwa ada yang tidak beres! Kaya-raya dan utang menumpuk adalah bukti ketidakberesan.
Kalau kau kaya-raya, kau pasti tidak akan berutang! Kalau kau sampai berutang, padahal kaya-raya, maka kemungkinannya adalah:
1. Kau orang kaya yang tolol bahkan idiot
2. Kau dipaksa untuk menjadi tolol, dan kau tidak bisa menolak
3. Kau sebenarnya tidak kaya, tapi pura-pura kaya
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 3 September 2018.
Gambar ini adalah posisi/besaran utang negara-negara di dunia. Saat melihat gambar ini, aku tidak bertanya "di mana posisi Indonesia", karena itu pertanyaan yang tidak adil. Ketika melihat gambar ini, yang kupikirkan, "Bagaimana bisa seluruh negara di dunia punya utang?"
Membandingkan utang Indonesia dengan utang-utang negara lain adalah perbandingan yang tidak adil, dan itu pula kampanye busuk yang selama ini dikoar-koarkan sebagian pihak. Utang berbanding lurus dengan kemampuan membayar, bukan dengan pihak lain yang sama-sama berutang.
Jika tweet barusan dianggap membingungkan, mari gunakan analogi sederhana. Si A punya utang 10.000, dan punya aset 1.000.000. Sementara Si B punya utang 1.000, dan punya aset 6.000. Dalam angka, utang Si A jauh lebih besar. Tapi dalam realitas, justru utang Si B yang lebih besar.
Membandingkan utang Indonesia dengan utang Amerika atau Jepang dengan dalih "utang mereka lebih besar" adalah perbandingan yang tidak adil sekaligus tendensius. Bukan besaran utang yang perlu diperhatikan, tapi kemampuan membayar yang patut dipikirkan. Mosok ngene wae ora paham?
Kalau aku punya utang 1 juta, misal, aku tak akan pusing, karena kapan pun bisa membayar. Tapi tetanggaku mungkin tak bisa tidur karena punya utang 100.000, karena tak bisa bayar. Jika tetanggaku bisa enteng mengatakan, "Tak perlu pusing, dia aja punya utang 1 juta," itu konyol.
Terkait utang (termasuk utang Indonesia, tentu saja) ingatlah selalu rumus ini: Jumlah utang berbanding lurus dengan kemampuan membayar, bukan dengan pihak lain yang sama-sama berutang. Melanggar rumus ini sama artinya membodohi diri sendiri (dan orang lain, kalau kau koar-koar).
Kalau kau berdebat dengan orang yang mencoba mempengaruhimu bahwa utang Indonesia "tidak seberapa" dan semacamnya, dan kau ingin mengalahkannya, tanyakan ini, "Sebenarnya, kepada siapa Indonesia (dan negara-negara lain) berutang?" Tak peduli sepintar apa pun, dia akan kelabakan.
Jangankan orang awam, bahkan Sri Mulyani pun akan kelabakan jika ditanya, "Kepada siapa sebenarnya Indonesia (dan negara-negara lain) berutang?"
Untuk bisa menemukan pertanyaan itu, apalagi untuk menjawabnya, kau harus membaca setidaknya 2.000 buku. Dan kau tahu aku serius.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 6 Juni 2018.
Membandingkan utang Indonesia dengan utang-utang negara lain adalah perbandingan yang tidak adil, dan itu pula kampanye busuk yang selama ini dikoar-koarkan sebagian pihak. Utang berbanding lurus dengan kemampuan membayar, bukan dengan pihak lain yang sama-sama berutang.
Jika tweet barusan dianggap membingungkan, mari gunakan analogi sederhana. Si A punya utang 10.000, dan punya aset 1.000.000. Sementara Si B punya utang 1.000, dan punya aset 6.000. Dalam angka, utang Si A jauh lebih besar. Tapi dalam realitas, justru utang Si B yang lebih besar.
Membandingkan utang Indonesia dengan utang Amerika atau Jepang dengan dalih "utang mereka lebih besar" adalah perbandingan yang tidak adil sekaligus tendensius. Bukan besaran utang yang perlu diperhatikan, tapi kemampuan membayar yang patut dipikirkan. Mosok ngene wae ora paham?
Kalau aku punya utang 1 juta, misal, aku tak akan pusing, karena kapan pun bisa membayar. Tapi tetanggaku mungkin tak bisa tidur karena punya utang 100.000, karena tak bisa bayar. Jika tetanggaku bisa enteng mengatakan, "Tak perlu pusing, dia aja punya utang 1 juta," itu konyol.
Terkait utang (termasuk utang Indonesia, tentu saja) ingatlah selalu rumus ini: Jumlah utang berbanding lurus dengan kemampuan membayar, bukan dengan pihak lain yang sama-sama berutang. Melanggar rumus ini sama artinya membodohi diri sendiri (dan orang lain, kalau kau koar-koar).
Kalau kau berdebat dengan orang yang mencoba mempengaruhimu bahwa utang Indonesia "tidak seberapa" dan semacamnya, dan kau ingin mengalahkannya, tanyakan ini, "Sebenarnya, kepada siapa Indonesia (dan negara-negara lain) berutang?" Tak peduli sepintar apa pun, dia akan kelabakan.
Jangankan orang awam, bahkan Sri Mulyani pun akan kelabakan jika ditanya, "Kepada siapa sebenarnya Indonesia (dan negara-negara lain) berutang?"
Untuk bisa menemukan pertanyaan itu, apalagi untuk menjawabnya, kau harus membaca setidaknya 2.000 buku. Dan kau tahu aku serius.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 6 Juni 2018.
“Kalau kau tidak peduli (terhadap AI), sebaiknya kau peduli!”
Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan menjadi topik panas akhir-akhir ini, khususnya untuk orang-orang yang punya ketertarikan. Bagi sebagian orang, Artificial Intelligence mungkin topik yang tergolong berat, sehingga tidak semua orang paham mengapa AI harus dikhawatirkan.
Oh, saya termasuk yang ikut khawatir dengan AI, karena—jika tidak dikendalikan dengan benar—AI adalah ancaman yang sangat nyata bagi umat manusia di masa depan. Dalam hal ini, saya setuju dengan Elon Musk yang terus menerus menegaskan, “Kalau kau tidak peduli (terhadap AI), sebaiknya kau peduli!”
Pada 2015 lalu, misalnya, di hadapan mahasiswa the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elon Musk membicarakan soal AI, dan terang-terangan menyatakan bahwa AI merupakan "ancaman eksistensial terbesar" manusia. Karena itu pula, belakangan, dia bersama 100 tokoh/ilmuwan lain menyusun petisi untuk mendesak PBB agar mengambil aksi terhadap bahaya AI.
Kenapa kita harus mengkhawatirkan AI?
Bagi yang masih bingung apa itu AI, silakan cari sendiri informasinya, karena ada banyak situs yang telah menjelaskan secara lengkap apa itu AI.
Catatan ini tidak akan menjelaskan apa itu AI, namun lebih pada alasan mengapa kita perlu mengkhawatirkan AI. Meski saya sudah berupaya menulis catatan ini sesederhana mungkin, sehingga bisa dipahami siapa pun, namun ada kemungkinan beberapa uraian dalam catatan ini cukup rumit. Karenanya, baca saja perlahan-lahan.
Pertama, mari kita lihat diri sendiri. Sebagai manusia, kita melalui proses yang panjang untuk tumbuh dan mengerti banyak hal. Setiap orang harus melewati fase demi fase, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lalu tua, dan proses itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Perjalanan seseorang dari bayi menjadi orang tua, bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Seiring perkembangan fisik yang kita alami, kita juga mengalami perkembangan nalar dan pikiran. Saat masih bayi, kita belum tahu apa-apa. Saat menjadi anak-anak, kita mulai tahu hal-hal tertentu, khususnya di sekitar kita, meski secara terbatas. Lalu pengetahuan kita bertambah saat remaja, dan terus bertambah ketika dewasa. Pada saat usia tua, kita pun telah mengumpulkan banyak pengetahuan yang kita serap selama puluhan tahun.
Berdasarkan ilustrasi itu, kita melihat bahwa manusia membutuhkan “evolusi” untuk mendapatkan pengetahuan, yang tergantung pada tingkat nalar. Saat TK, kita hanya bisa memahami hal-hal yang sesuai otak anak TK. Lalu meningkat saat SD, SMP, dan seterusnya. Otak kita tidak bisa serta-merta mencerna hal-hal berat yang ditujukan untuk anak SMA, jika waktu itu kita masih TK. Artinya, kita butuh proses, dan proses itu bisa sangat lama.
Selain itu, manusia juga mengalami perubahan fisik. Orang yang sangat kuat pada waktu muda, akan mulai lemah saat memasuki usia tua. Itu hal alami yang terjadi pada semua orang, sehingga tidak perlu dibantah. Pada akhirnya, seiring tubuh yang kian lemah, setiap manusia akan mati. Ketika manusia mati, berakhir pula semua yang ia ketahui saat masih hidup. Dalam hal itu, sebagian orang mewariskan pengetahuan yang mereka miliki—biasanya secara tertulis—sehingga bisa diwarisi generasi selanjutnya.
Karena generasi selanjutnya mendapatkan warisan pengetahuan dari generasi sebelumnya, generasi yang baru pun bisa diharapkan lebih pintar dari generasi terdahulu. Dan kenyataannya memang begitu. Fakta bahwa kita hari ini mengenal internet, sementara kakek-nenek kita tidak mengenal, adalah salah satu bukti mencolok bahwa generasi kita jauh lebih pintar dibanding generasi zaman dulu (setidaknya generasi zaman kakek-nenek).
Kita lihat...? Manusia membutuhkan proses untuk segala sesuatu. Dari pertumbuhan fisik sampai pertumbuhan nalar dan pengetahuan, kita semua membutuhkan proses. Dan proses itu bisa memakan waktu puluhan tahun. Bahkan untuk hal “sepele” seperti bermain catur pun, kita membutuhkan proses pembelajaran, yang bisa jadi cukup lama. Tidak ada manusia yang ujug-ujug lahir, lalu bisa bermain catur.
Kini, di zaman kita, anggap saja manusia telah mencapai puncak kecerdasan. Manusia di zaman sekarang bisa dibilang seratus kali lebih cerdas dibanding manusia yang hidup seratus tahun lalu. Karena kecerdasan luar biasa pula, manusia di zaman kita bisa menciptakan sesuatu yang disebut Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence, yaitu entitas kecerdasan mirip manusia, tapi dibuat manusia, dan di luar manusia.
Sampai di sini, kita sampai pada pertanyaan yang sangat penting.
Jika manusia bisa menciptakan kecerdasan lain mirip dirinya, mungkinkah manusia akan puas menciptakan kecerdasan yang lebih rendah darinya?
Jawabannya jelas, tidak!
Karena, buat apa repot-repot menciptakan kecerdasan buatan, kalau kecerdasan itu tidak berguna? Agar kecerdasan buatan bisa berguna, ia harus secerdas manusia penciptanya, atau bahkan harus lebih cerdas dari manusia penciptanya. Karena tujuan menciptakan kecerdasan buatan adalah untuk “mengalihkan” banyak hal kepadanya, sehingga manusia bisa terbebas dari proses!
Inilah asal usul mengapa manusia sampai menciptakan kecerdasan buatan—sesuatu yang mungkin tak terpikirkan banyak orang. Ketika suatu entitas kecerdasan menciptakan entitas kecerdasan lain, entitas buatan akan dirancang lebih cerdas dari sang pembuat. Karena tujuannya memang untuk “memangkas” proses!
Jika kalimat itu masih sulit dipahami, silakan tonton film seri Iron Man sekali lagi. Dalam serial Iron Man, kita tahu Tony Stark punya kecerdasan buatan yang ia namai Jarvis, dan kecerdasan buatan itu pula yang membantu Tony Stark pada banyak hal, termasuk merancang kecerdasan buatan lain (Ultron) yang lalu muncul dalam film The Avengers 2.
Perhatikan fakta penting berikut ini.
Jarvis diciptakan oleh Tony Stark. Secara logika, Tony Stark tentu lebih cerdas dari Jarvis, karena ia yang menciptakan Jarvis, karena Jarvis hanya kecerdasan buatan yang dirancang oleh Tony Stark. Pencipta pasti lebih hebat dibanding barang ciptaannya, kan?
Salah!
Ketika entitas kecerdasan menciptakan entitas kecerdasan lain, justru entitas buatan yang akan lebih cerdas dari entitas penciptanya!
Faktanya memang Tony Stark yang menciptakan Jarvis. Tetapi, sebenarnya, Jarvis lebih cerdas dari Tony Stark. Dalam ilustrasi yang mudah, Tony Stark—tak peduli dia secerdas apa pun—harus melalui proses sebagaimana layaknya manusia. Artinya, dia membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang menjadikannya cerdas.
Berbeda dengan Jarvis. Sebagai kecerdasan buatan, dia tidak membutuhkan proses lama seperti Tony Stark, atau manusia umumnya, dalam menyerap pengetahuan apa pun.
Sebagai kecerdasan buatan, Jarvis bisa mempelajari banyak pengetahuan dalam waktu jauh lebih singkat, dalam durasi jam, menit, atau bahkan detik! Jarvis tidak butuh proses bertahun-tahun. Cukup sodorkan sesuatu kepadanya, dan dia akan langsung memahami. Bahkan, jika manusia bisa lupa, Jarvis tidak pernah lupa!
Did you see that?
Ketika entitas kecerdasan menciptakan entitas kecerdasan lain, entitas buatan akan lebih cerdas dari kecerdasan pembuatnya... dan itulah akar motivasi manusia menciptakan kecerdasan buatan. Untuk memangkas proses.
Dengan memiliki Jarvis, Tony Stark tidak perlu mempelajari banyak hal yang akan butuh waktu sangat lama, karena hal-hal tertentu yang rumit dan sangat teknis bisa diserahkan kepada Jarvis. Tony Stark tinggal menikmati hasilnya. Dia cukup bertanya, dan Jarvis akan menjawab.
Sekarang kita masuk pada topik inti, mengapa kecerdasan buatan atau AI patut dikhawatirkan.
Ingat kembali fakta tadi. Ketika entitas kecerdasan menciptakan entitas kecerdasan lain, entitas buatan akan lebih cerdas dari kecerdasan pembuatnya.
Sekarang bayangkan saja, saat ini manusia menciptakan kecerdasan buatan. Sebut saja AI-1. Dengan kecerdasan buatan tersebut, manusia bisa menjalankan banyak hal tanpa perlu repot-repot, karena AI-1 lebih cerdas dari manusia, dan bisa mengerjakan banyak hal.
Seiring perkembangan, dan seiring tantangan modernisasi teknologi yang kian rumit, tingkat kecerdasan AI-1 mulai kewalahan dalam menghadapi masalah. Sampai di situ, AI-1 yang cerdas lalu berpikir, “Apa salahnya kalau aku menciptakan kecerdasan buatan?”
Itu pikiran yang sama dengan manusia, ketika manusia pertama kali menciptakan kecerdasan buatan. Manusia menciptakan kecerdasan buatan, karena berharap bisa menyelesaikan banyak hal dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dalam satu titik tertentu, kecerdasan buatan juga bisa berpikir seperti itu—mereka ingin menyelesaikan sesuatu dengan lebih mudah dan lebih cepat. Maka, AI-1—yang merupakan kecerdasan buatan manusia—kemudian menciptakan kecerdasan buatan lain. Sebut saja AI-2.
Jika hal itu telah terjadi, dunia akan mengalami lompatan teknologi yang tak bisa lagi dibayangkan apalagi diperkirakan. Segala hal bisa terjadi... baik maupun buruk. Ketika sebuah kecerdasan buatan telah menciptakan kecerdasan buatan lain, nasib umat manusia benar-benar akan sampai di titik nadir.
Sekarang kita kembali ke awal. Ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan, bagaimana pun manusia tetap berpikir untuk bisa mengendalikan kecerdasan buatan tersebut. Hal itu dilatari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk biologis, yang tidak hanya memiliki otak untuk berpikir, namun juga memiliki standar moral. Karenanya, manusia akan memastikan kecerdasan buatannya tidak akan sampai berbalik melawan manusia.
Tetapi... kecerdasan buatan tidak akan berpikir seperti itu!
Ketika kecerdasan buatan telah mampu menciptakan kecerdasan buatan lain, mereka tidak berpikir sebagaimana manusia, karena mereka bukan makhluk biologis, dan—tentu saja—tidak memahami (atau tidak peduli) standar moral.
Ketika kecerdasan buatan AI-1 menciptakan AI-2, hampir bisa dipastikan AI-2 akan lebih cerdas dari AI-1. Dan AI-1 tidak akan peduli bagaimana nasib dirinya terkait hal itu, karena—sebagai kecerdasan buatan—tugasnya hanya melakukan yang harus dilakukan. Lalu, ketika AI-2 telah tercipta, selalu ada kemungkinan AI-2 akan menciptakan kecerdasan buatan lain, sebut saja AI-3. Dan begitu seterusnya.
Karena sangat cerdas dan tidak dihambat faktor biologis, AI-1 dan seterusnya tidak butuh waktu lama sebagaimana manusia ketika menciptakan kecerdasan buatan pertama kali. Dan ketika kenyataan semacam itu benar-benar terjadi, maka umat manusia—cepat atau lambat—akan berhadapan dengan kecerdasan buatan yang memiliki kecerdasan jutaan kali lipat dari kecerdasan manusia mana pun. Sosok itu, sebut saja, AI-100.
Sekarang pikirkan... apa yang kira-kira akan dilakukan kecerdasan luar biasa semacam itu terhadap umat manusia? Jika AI-100, yang memiliki kecerdaan jutaan kali lipat dibanding manusia mana pun, berhadap-hadapan dengan umat manusia... apa yang kira-kira akan dilakukannya?
Ketika manusia berhadapan dengan kecerdasan AI-100, ada banyak masalah yang patut dikhawatirkan. Pertama, manusia kalah cerdas. Kedua, manusia bisa sakit dan mati. Ketiga, manusia punya rasa takut dan khawatir. Daftar ini bisa dilanjutkan, yang semuanya merupakan kelemahan umat manusia—sesuatu yang tidak dimiliki AI-100. Sebagai kecerdasan buatan, AI-100 tidak punya rasa takut dan khawatir, tidak sakit dan mati, dan—di atas segalanya—dia jutaan kali lebih cerdas dari kita.
Bayangan semacam itu mengingatkan kita pada analogi “semut dan sepatu bot” yang dibicarakan Loki dan Nick Fury dalam film The Avengers. Kita adalah “semut”—kecil, tak berdaya. Sementara AI-100 adalah “sepatu bot”—luar biasa cerdas dan berkuasa. Dan sebagaimana manusia yang punya kecenderungan menindas yang lemah, selalu ada kemungkinan hal sama terjadi ketika manusia ada di pihak lemah.
Kenyataan semacam itulah yang dikhawatirkan Elon Musk dan orang-orang lain, hingga mereka sampai mengirim petisi kepada PBB agar ikut turun tangan dalam mengendalikan AI yang saat ini terus dikembangkan. Sebagian manusia, saat ini, telah mengalami “lupa diri” dan terlena pada kehebatan teknologi, hingga mereka mungkin tak sempat memikirkan dampaknya di masa depan.
Memang, AI yang ada saat ini—secanggih apa pun—masih dalam tahap “primitif”, dalam arti masih ada di bawah kendali manusia. Tetapi, bukankah manusia juga mengalami hal serupa? Manusia pernah mengalami peradaban primitif, merasa dikendalikan oleh “hal-hal di luar mereka”, sampai kemudian menemukan kecerdasannya sendiri... hingga akhirnya mampu menciptakan kecerdasan buatan di luar dirinya. Tidakkah hal serupa juga akan terjadi pada AI?
Selain Elon Musk, ilmuwan lain yang ikut mengkhawatirkan hal ini adalah Stephen Hawking. Dia menggarisbawahi bahwa teknologi primitif AI yang digunakan saat ini sudah sangat berguna bagi manusia, namun ia takut terhadap konsekuensi menciptakan sesuatu yang dapat bersaing atau bahkan melebihi kemampuan manusia.
Hawking menyatakan, “AI akan dapat berjalan sendiri, dan mendesain ulang dirinya sendiri pada tingkatan yang semakin meningkat. Manusia, yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat, tidak bisa bersaing, dan akan digantikan."
Jadi, jika yang dikhawatirkan Elon Musk dan Stephen Hawking—serta para ilmuwan lain—benar-benar menjadi kenyataan, maka akan tiba suatu masa ketika umat manusia harus berhadap-hadapan dengan kecerdasan buatan, yang jutaan kali lebih cerdas dibanding kecerdasan manusia mana pun. Dan jika benar-benar terjadi, umat manusia di zaman itu mungkin akan bertanya-tanya... di manakah Tuhan sebenarnya?
Ada aplikasi penyedia bacaan yang telah disuntik dana 100 miliar. Tapi kualitas aplikasi itu sangat menyedihkan. Uang banyak saja tampaknya memang tak cukup, jika tidak didukung SDM yang bagus. Itu seperti memasukkan air seember ke dalam cangkir. Luber, mubazir, dan sia-sia.
Ada orang-orang yang punya banyak uang dan ingin menciptakan sesuatu yang hebat, tapi tidak mampu menjangkau orang-orang terbaik. Di sisi lain, ada orang-orang dengan bakat hebat tapi cuma bisa bermimpi, karena tak punya modal kapital. Sepertinya, itu masalah klasik banyak orang.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 18 Maret 2018.
Ada orang-orang yang punya banyak uang dan ingin menciptakan sesuatu yang hebat, tapi tidak mampu menjangkau orang-orang terbaik. Di sisi lain, ada orang-orang dengan bakat hebat tapi cuma bisa bermimpi, karena tak punya modal kapital. Sepertinya, itu masalah klasik banyak orang.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 18 Maret 2018.
Pengetahuan tidak diperoleh secara kebetulan,
tapi harus dicari dengan semangat dan disertai ketekunan.
—Abigail Adams, sastrawan
Tanpa pengetahuan, hidup tak lebih dari bayangan kematian.
—Moliere, sastrawan
Sains adalah suatu cara berpikir
lebih dari sekadar tubuh pengetahuan.
—Carl Sagan, ilmuwan
Jika saya masuk ke sebuah kelas, dan bertanya pada orang-orang di dalamnya, “Adakah di antara kalian yang pernah membaca ensiklopedi?” Kemungkinan besar akan ada cukup banyak orang yang mengacungkan jari, menunjukkan bahwa mereka pernah membaca ensiklopedi.
Tetapi, jika saya bertanya, “Adakah di antara kalian yang pernah mengkhatamkan ensiklopedi?” Kemungkinan besar tidak ada yang mengacungkan jari, menunjukkan tidak satu pun dari mereka yang pernah mengkhatamkan ensiklopedi.
Sepertinya memang sangat jarang—bahkan hampir tidak ada—orang yang mengkhatamkan ensiklopedi. Karena rata-rata orang menganggap ensiklopedi bukan jenis buku untuk dikhatamkan, meski digunakan sebagai referensi.
Karenanya, ketika orang mengambil ensiklopedi dan membuka isinya, rata-rata mereka langsung menuju halaman yang dicari atau diinginkan, lalu membaca entri di halaman tersebut. Setelah selesai, ensiklopedi pun ditutup.
Kenyataan itu sempat menggelisahkan pikiran saya. Ensiklopedi adalah buku/bacaan penting, yang—menurut saya—seharusnya dibaca, dipelajari, dan dikhatamkan seisi-isinya. Jadi, saya bertanya-tanya, kenapa rata-rata orang tidak tertarik membaca-untuk-mengkhatamkan ensiklopedi?
Pertanyaan dan kegelisahan itulah yang lalu menuntun saya untuk menulis ensiklopedi versi saya sendiri, dan lahirlah Ensiklopedi Sains yang kini terbit dalam tiga jilid sekaligus.
Sebagaimana namanya, Ensiklopedi Sains berisi pembahasan seputar ilmu pengetahuan, meliputi bumi, ruang angkasa, peradaban dan kebudayaan, manusia, flora fauna, sejarah, tokoh dunia, teknologi, dan hal-hal penting lain di alam semesta.
Dalam tiga jilid besar Ensiklopedi Sains, saya menyusun ensiklopedi dengan bahasa populer yang mudah dicerna, dengan sistematika yang akan membuat pembaca terdorong untuk terus membaca, entri per entri, lembar per lembar, bab per bab, sampai akhirnya khatam. Jika kalian ingin mengkhatamkan ensiklopedi—setidaknya satu kali seumur hidup—Ensiklopedi Sains bisa menjadi pilihan.
Ensiklopedi Sains diterbitkan oleh Arruz Media, penerbit yang juga menerbitkan “karya raksasa” saya sebelumnya, Sejarah dan Pengetahuan Dunia Abad 20. Jika buku sebelumnya terwujud dalam sebuah buku besar sekaligus tebal, Ensiklopedi Sains terwujud dalam tiga buku besar sekaligus tebal, dengan sampul hardcover, isi art paper, dan full colour!
Terima kasih buat Arruz Media yang telah melahirkan “anak saya” dalam wujudnya yang spektakuler. Sebagai penulis—dan sebagai bocah, tentu saja—saya benar-benar bangga memilikinya!
Ensiklopedi Sains
ISBN: 978-602-303-004-7 (jilid lengkap)
ISBN: 978-602-313-006-1 (jilid 1)
ISBN: 978-602-313-007-8 (jilid 2)
ISBN: 978-602-313-008-5 (jilid 3)
Penerbit: Arruz Media
Dimensi: 19,5 x 26,5 cm
Sampul: Hardcover
Isi: Art paper, full colour
Tebal: 1.060 halaman
Berat: 15 kilogram
Harga: Rp1,5 juta
Buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku terkemuka
di seluruh Indonesia, atau melalui marketplace
dan toko-toko buku online di internet.
Kemarin, daerah-daerah Pantura dilanda banjir cukup tinggi. Bukan banjir air hujan, tapi banjir air dari pantai. Ombak bergulung tinggi, dan dampaknya menjadi banjir hingga jarak sangat jauh. Ratusan atau mungkin ribuan rumah terendam air. Bahkan ada yang sampai sekarang.
Bagaimana bisa ombak pantai menyebabkan banjir, hingga ke tempat-tempat yang jauhnya ratusan meter? Jawabannya mungkin terdengar rumit dan menakjubkan. Tetapi, yang lebih menakjubkan adalah... daratan rumah di Pantura yang terendam banjir itu dulunya berada di dasar lautan!
Di masa lalu, kawasan Pantura sebenarnya tidak ada, karena wilayah itu belum menjadi daratan. Begitu pun, rumah-rumah dan bangunan di sana juga tidak ada, karena semula berupa lautan. Proses ribuan tahun membentuk pengendapan, yang lalu berubah menjadi daratan seperti sekarang.
Kisah pembentukan daratan yang kini disebut Pantura mungkin kurang menarik, dan kurang spektakuler. Prosesnya sama dengan kisah pembentukan Puncak Jaya (Carstensz Pyramide), yang kini menjadi salah satu puncak tertinggi di dunia.
Puncak Jaya (Carstensz Pyramide) adalah puncak tertinggi di dunia. Berada di puncak Jayawijaya, Carstensz Pyramide memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Tapi bukan itu yang menakjubkan. Yang menakjubkan... puncak tertinggi itu dulunya berada di dasar laut.
Menatap Carstensz Pyramide adalah menatap waktu... yang dimulai jutaan tahun lalu.
Pada 250 juta tahun lalu, Bumi hanya memiliki satu benua, bernama Pangea. Pada kurun 240 juta-65 juta tahun lalu, Pangea pecah menjadi dua, membentuk Benua Laurasia dan Benua Eurasia, yang menjadi cikal bakal pembentukan benua dan pegunungan yang saat ini ada di seluruh dunia.
Pada kurun waktu itu pula, Benua Eurasia—yang berada di belahan bumi bagian selatan—pecah kembali menjadi Benua Gondwana, yang di kemudian hari menjadi daratan Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia.
Pada waktu itu, Benua Australia dengan benua-benua lain dipisahkan oleh lautan. Di lautan bagian utara, sebuah batuan mengendap, yang kelak menjadi bagian dari Australia.
Pengendapan yang sangat intensif akhirnya mengangkat sedimen batu ke atas permukaan laut. Proses pengangkatan itu tentu berdasarkan skala waktu geologi, dengan kecepatan 2,5 km per sejuta tahun.
Proses pengendapan itu masih ditambah oleh terjadinya tumbukan lempeng, antara lempeng Indo-Pasifik dengan Indo-Australia, di dasar laut. Tumbukan lempeng menghasilkan busur pulau, yang menjadi cikal bakal pulau dan pegunungan di Papua.
Pulau Papua mulai terbentuk pada 60 juta tahun lalu. Saat itu, pulau ini masih berada di dasar laut, yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal dari Benua Australia, dalam kurun waktu panjang, menghasilkan daratan baru yang kini bernama Papua.
Akhirnya, proses pengangkatan yang terus-menerus, akibat sedimentasi dan disertai kejadian tektonik bawah laut, dalam kurun waktu jutaan tahun, menghasilkan pegunungan tinggi Jayawijaya seperti yang kita lihat saat ini.
Apa buktinya kalau Papua serta pegunungan tingginya pernah menjadi bagian dari dasar laut yang dalam? Buktinya mudah, di sana ada banyak fosil laut yang saat ini masih tertinggal di bebatuan Jayawijaya.
Meski berada di ketinggian 4.884 mdpl, fosil kerang laut, misalnya, dapat dilihat pada batuan gamping dan klastik yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Karena itu, selain menjadi surga para pendaki, Jayawijaya juga menjadi surga para peneliti geologi.
Dan, omong-omong, kira-kira seperti itu pulalah terbentuknya kawasan atau daratan yang sekarang kita sebut Pantura. Karenanya, orang-orang tua di sana kerap berkata, "Tanah yang kita pijak ini dulunya ada di dasar laut, Nak." Meski mungkin terdengar fantastis, mereka benar.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 24 Mei 2018.
Bagaimana bisa ombak pantai menyebabkan banjir, hingga ke tempat-tempat yang jauhnya ratusan meter? Jawabannya mungkin terdengar rumit dan menakjubkan. Tetapi, yang lebih menakjubkan adalah... daratan rumah di Pantura yang terendam banjir itu dulunya berada di dasar lautan!
Di masa lalu, kawasan Pantura sebenarnya tidak ada, karena wilayah itu belum menjadi daratan. Begitu pun, rumah-rumah dan bangunan di sana juga tidak ada, karena semula berupa lautan. Proses ribuan tahun membentuk pengendapan, yang lalu berubah menjadi daratan seperti sekarang.
Kisah pembentukan daratan yang kini disebut Pantura mungkin kurang menarik, dan kurang spektakuler. Prosesnya sama dengan kisah pembentukan Puncak Jaya (Carstensz Pyramide), yang kini menjadi salah satu puncak tertinggi di dunia.
Puncak Jaya (Carstensz Pyramide) adalah puncak tertinggi di dunia. Berada di puncak Jayawijaya, Carstensz Pyramide memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Tapi bukan itu yang menakjubkan. Yang menakjubkan... puncak tertinggi itu dulunya berada di dasar laut.
Menatap Carstensz Pyramide adalah menatap waktu... yang dimulai jutaan tahun lalu.
Pada 250 juta tahun lalu, Bumi hanya memiliki satu benua, bernama Pangea. Pada kurun 240 juta-65 juta tahun lalu, Pangea pecah menjadi dua, membentuk Benua Laurasia dan Benua Eurasia, yang menjadi cikal bakal pembentukan benua dan pegunungan yang saat ini ada di seluruh dunia.
Pada kurun waktu itu pula, Benua Eurasia—yang berada di belahan bumi bagian selatan—pecah kembali menjadi Benua Gondwana, yang di kemudian hari menjadi daratan Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia.
Pada waktu itu, Benua Australia dengan benua-benua lain dipisahkan oleh lautan. Di lautan bagian utara, sebuah batuan mengendap, yang kelak menjadi bagian dari Australia.
Pengendapan yang sangat intensif akhirnya mengangkat sedimen batu ke atas permukaan laut. Proses pengangkatan itu tentu berdasarkan skala waktu geologi, dengan kecepatan 2,5 km per sejuta tahun.
Proses pengendapan itu masih ditambah oleh terjadinya tumbukan lempeng, antara lempeng Indo-Pasifik dengan Indo-Australia, di dasar laut. Tumbukan lempeng menghasilkan busur pulau, yang menjadi cikal bakal pulau dan pegunungan di Papua.
Pulau Papua mulai terbentuk pada 60 juta tahun lalu. Saat itu, pulau ini masih berada di dasar laut, yang terbentuk oleh bebatuan sedimen. Pengendapan intensif yang berasal dari Benua Australia, dalam kurun waktu panjang, menghasilkan daratan baru yang kini bernama Papua.
Akhirnya, proses pengangkatan yang terus-menerus, akibat sedimentasi dan disertai kejadian tektonik bawah laut, dalam kurun waktu jutaan tahun, menghasilkan pegunungan tinggi Jayawijaya seperti yang kita lihat saat ini.
Apa buktinya kalau Papua serta pegunungan tingginya pernah menjadi bagian dari dasar laut yang dalam? Buktinya mudah, di sana ada banyak fosil laut yang saat ini masih tertinggal di bebatuan Jayawijaya.
Meski berada di ketinggian 4.884 mdpl, fosil kerang laut, misalnya, dapat dilihat pada batuan gamping dan klastik yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Karena itu, selain menjadi surga para pendaki, Jayawijaya juga menjadi surga para peneliti geologi.
Dan, omong-omong, kira-kira seperti itu pulalah terbentuknya kawasan atau daratan yang sekarang kita sebut Pantura. Karenanya, orang-orang tua di sana kerap berkata, "Tanah yang kita pijak ini dulunya ada di dasar laut, Nak." Meski mungkin terdengar fantastis, mereka benar.
*) Ditranskrip dari timeline @noffret, 24 Mei 2018.
Dalam film The Avengers, ada adegan Tony Stark dan Pepper Pots bercakap-cakap di dalam rumah. Adegan itu dimulai ketika Tony Stark (Iron Man) baru sampai di rumah, kemudian melepaskan pakaian besinya, dan disambut Pepper Pots dengan manis, lalu mereka menikmati dua gelas minuman entah apa.
Dan bercakap-cakap.
Selama percakapan berlangsung, Pepper Pots—yang mengenakan celana pendek—tampak berjalan ke sana kemari bertelanjang kaki. Dan pemandangan itu menjadi adegan dalam The Avengers yang saya ulang berkali-kali.
Entah kenapa, saya selalu senang menyaksikan perempuan dewasa berjalan telanjang kaki di lantai rumah. Atau di karpet rumah. Rasanya, bagi saya, seperti menyaksikan salah satu keindahan menakjubkan. Saya pikir, kebahagiaan memiliki seorang pasangan wanita di rumah adalah menyaksikannya berjalan ke sana kemari bertelanjang kaki.
Seperti Pepper Pots. Dalam film The Avengers.
Pepper Pots, bagi Tony Stark, bukan hanya asisten pribadi, bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga seorang mbakyu. Dalam serial Iron Man, kita melihat besarnya peran Pepper Pots dalam menghadapi Tony Stark yang kadang kekanak-kanakan. Oh, well, semua superhero punya mbakyu, bahkan Tony Stark yang genius.
Tiba-tiba saya merasa menemukan tujuan penting memiliki pasangan. Saya ingin melihat pasangan saya berjalan dengan anggun, bertelanjang kaki, di atas lantai atau karpet rumah. Rasanya pasti menyenangkan.
Dan pasangan itu harus seorang wanita dewasa yang anggun. Seorang mbakyu.
Seperti Pepper Pots. Dalam film The Avengers.
Dan bercakap-cakap.
Selama percakapan berlangsung, Pepper Pots—yang mengenakan celana pendek—tampak berjalan ke sana kemari bertelanjang kaki. Dan pemandangan itu menjadi adegan dalam The Avengers yang saya ulang berkali-kali.
Entah kenapa, saya selalu senang menyaksikan perempuan dewasa berjalan telanjang kaki di lantai rumah. Atau di karpet rumah. Rasanya, bagi saya, seperti menyaksikan salah satu keindahan menakjubkan. Saya pikir, kebahagiaan memiliki seorang pasangan wanita di rumah adalah menyaksikannya berjalan ke sana kemari bertelanjang kaki.
Seperti Pepper Pots. Dalam film The Avengers.
Pepper Pots, bagi Tony Stark, bukan hanya asisten pribadi, bukan hanya seorang kekasih, tetapi juga seorang mbakyu. Dalam serial Iron Man, kita melihat besarnya peran Pepper Pots dalam menghadapi Tony Stark yang kadang kekanak-kanakan. Oh, well, semua superhero punya mbakyu, bahkan Tony Stark yang genius.
Tiba-tiba saya merasa menemukan tujuan penting memiliki pasangan. Saya ingin melihat pasangan saya berjalan dengan anggun, bertelanjang kaki, di atas lantai atau karpet rumah. Rasanya pasti menyenangkan.
Dan pasangan itu harus seorang wanita dewasa yang anggun. Seorang mbakyu.
Seperti Pepper Pots. Dalam film The Avengers.
Langganan:
Komentar (Atom)

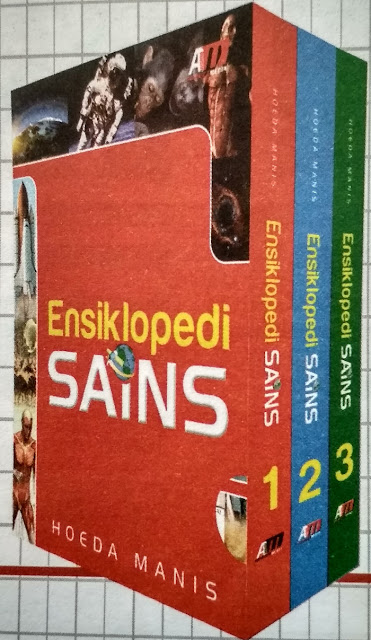



- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact